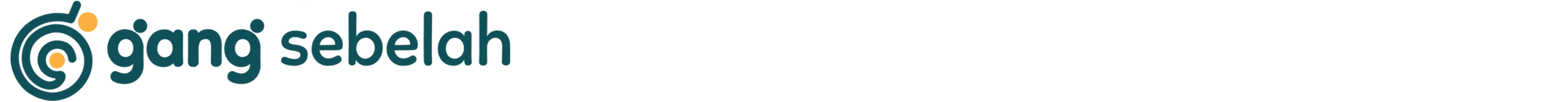I/
Ketahuilah, Alinda, ini surat terakhirku untukmu. Bila ada waktu, bacalah di ujung dermaga Geladak Gede sembari memandang tongkang kapal yang tengah mengangkut batu bara, atau saat kau merutuki kapal curah Vietnam yang membawa ribuan ton amoniak hingga membuatmu berlayar jauh ke Madura.
Tak perlu engkau gusar bila nanti aku tak lagi berkirim kabar, sebab aku telah benamkan segala jarak pandang yang akan menjauhkan kita. Bahkan waktu, Alinda, aku telah memintanya bersetubuh denganmu, sebab waktu akan selalu perawan bagi mereka yang memiliki kehidupan. Tak seperti aku di sini. Untuk sekadar menuai benih di pekarangan, terasa betul ruh dalam tubuhku tercerabut meninggalkan tulang belulang lalu menetap di buluh talang.
Sungguh, Alinda, hidup di tanah Pandhalungan yang bernapas dari daun tembakau, aku mesti melepas doa penghabisan lantaran tak sedikit sawah-sawah berubah bentuk menjadi perumahan. Gumuk-gumuk dikeruk. Pasir dan bebatu padas diangkut ke kota guna membangun gedung menjulang. Dan sekarang, aku terpaksa mengikhlaskan kenangan lantaran sawah dan gumuk tempatku memetakan harapan, kini tunduk di bawah langit yang berkerudung bianglala.
Aku masih ingat betul. Saat itu, usiaku sepuluh tahun. Mamak berlari-lari dari dapur sembari menjinjing sampir lantaran langit yang semula terang benderang, tiba-tiba menaruh pecahan awan gelap. Aku lintang pukang menuju halaman depan demi memungut tembakau yang digempur hujan. Daun-daun yang awalnya kering, terlihat kusut penuh air. Aku tahu, lembabnya wajah Mamak bukan basah sebab hujan melainkan mata air yang turun dari kedua matanya.
“Tak apa,” kata Mamak seusai memungut daun terakhir. “Masih bisa Mamak angin-anginkan.”
“Tapi, Mak. Mana ada yang mau beli kalau hitam begini?”
Mamak tak jawab. Ia segera mengangkut tembakau menuju dapur. Di atas tembikar lusuh, Mamak duduk sembari melesatkan batang mahoni ke dalam tungku. Asap menguar memenuhi reng-reng yang terpasang melintang di atas kasau. Mendapati bara api kian menyala, Mamak menaruh kuali besar yang berisi air. Di atas penutup kuali itulah, Mamak menata sehelai demi sehelai daun tembakau.
Bilamana asap kian membubung, lekas-lekas Mamak halau menggunakan klaras agar tak sampai menjadikan daun tembakau kian menghitam. Tapi, bilamana panas tutup kuali tak disadari Mamak dan menjadikan tembakau lebih kerontang, Mamak mengelus dada dalam-dalam. Sungguh, Alinda, merawat tembakau tak ubahnya merawat bayi. Disayang saat kecil, tapi saat dewasa bisa jadi menjelma Malin Kundang manakala harga tembakau menjungkalkan petani.
Purwanti tersentak saat mendengar derap langkah Bahrus di samping kobhung. Lekas-lekas ia melipat surat itu dan menaruhnya ke dalam kutang. Sialnya, belum selesai memasang kancing, Bahrus keburu muncul di pintu. Rambutnya kusut masai sementara kedua matanya menyala serupa nyala api neraka. Tanpa bertanya sepatah kata, lelaki itu menjambak rambut sang istri lalu menyeretnya sampai keluar kamar.
“Harus berapa ribu kali kukatakan padamu, Pur? Jangan kerja di gudang tembakau!”
Bahrus kian mencak-mencak tatkala mendapati Purwanti sesenggukan. Lelaki itu lantas berlari ke dapur, memungut piring, gelas dan panci, lalu dilemparkan ke dinding. Purwanti menutupi telinga saat pecahan kaca menyeruak ke atas lantai. Tapi, Bahrus kembali menyeret Purwanti menuju kamar, dan menendangnya sampai terjungkal.
“Tulikah telingamu itu, ha? Butakah matamu selama ini?”
“Tapi, utang kita sudah menumpuk, Kak. Puluhan juta.”
“Lihat! Lihat ini!” teriak Bahrus seraya menjumput rambut Purwanti dan membenturkan kepala istrinya ke dinding berulang kali. “Belum kerja di gudang saja, kau berani bantah suamimu. Apalagi kalau sudah dapat uang sendiri.”
Purwanti kian sesenggukan. Ia dekap kedua lututnya sembari menggigit bibir bawah agar tak mengeluarkan suara. Purwanti baru bernapas lega manakala mendapati Bahrus beranjak ke kobhung. Lekas-lekas ia memungut surat di dalam kutang.
Alinda, Sahabatku. Bila nanti angin utara tak lagi membawa kabar dari timur Jawa, maka inilah akhir dari waktu yang kian garam. Aku amat berterima kasih atas persahabatan kita selama ini. Percayalah, Alinda, kalau bukan engkau, tak lagi ada tempatku mengadu, lantaran di sini, segala cerita adalah kobaran matahari yang harus aku simpan di dada seorang diri.
Saat suamiku berniat menjual sepetak ladang yang bersebelahan dengan gumuk yang menjadi incaran investor perumahan, mati-matian aku memohon agar tak dilepas. Tapi, Alinda, lahir sebagai perempuan harus siap menerima takdir pincang. Jangankan didengar, suaraku justru sumbang sebelum berhasil mengutarakan seluruh pandangan. Mulutku ditampar. Tubuh diganyang. Padahal aku sekadar meminta diri, jika ladang dilepas, di mana lagi aku menanam tembakau yang menjadi urat nadi? Atau kalau gumuk dikeruk dalam-dalam, dari mana mata air akan menghidupi kehidupan?
“Kau pergi saja, lha, ke kangai. Jangan malas jadi perempuan!”
Itulah yang suamiku ucapkan saat aku berkata, gumuk adalah paku dari bumi. Bila pepohonan tercerabut, sumber mata air tak lagi keluar.
Alinda, kawan karibku. Sekiranya engkau bersedia, biarlah segala hikayat yang aku tulis sejak surat pertama, menjadi saksi jika perempuan seperti aku terpaksa tinggal di dua tempat. Pertama, di dalam rumah yang tiap saat menerima amuk serapah. Kedua, di dalam tulang rusuk lelaki.
Kau tahu, Alinda, jangankan bekerja demi mencicil utang di mana suamiku mencak-mencak tak keruan lantaran gajiku bakal lebih tinggi dari kerjanya yang serabutan, untuk sekadar bersetubuh saja di atas ranjang, perempuan seperti aku hanya punya satu pilihan, yakni lubang farji dipaksa menerima lesatan batang lelaki berulang-ulang, dan tak boleh menolak sekali pun datang bulan.
Alinda, kali ini aku tak lagi menginginkan surat balasan darimu. Simpanlah bila kau ingin simpan. Ceritakan bila kau ingin ceritakan. Aku kira, sudah sampai waktuku di penghujung penghabisan. Terima kasih atas segalanya. Semoga kita masih berjumpa di kehidupan selanjutnya.
Salam hangat dari sahabatmu di tanah Tenggara.
Purwanti
II/
Gemetar aku membaca suratmu ini, Pur. Tapi, aku jauh lebih gemetar lantaran baru saja aku temukan berita di gawai, kalau di timur Jawa, ada perempuan muda gantung diri tanpa mengenakan kutang dan celana dalam, dan ternyata itu dirimu, Pur.
Heboh Kasus Perempuan di Jember Bunuh Diri Tanpa Sehelai Pakaian
JEMBER-Publik di Kabupaten Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan adanya kasus bunuh diri. Purwanti (29 tahun) yang tinggal di Dusun Ledok, Sidomukti, ditemukan tewas di kamarnya tanpa mengenakan sehelai pakaian pada Kamis (23/11/2023).
Purwanti ditemukan oleh suaminya dengan kondisi leher terlilit mukena yang diikatkan pada bagian atas jendela. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, Kapolsek Mayang menyimpulkan jika motif yang bersangkutan melakukan bunuh diri karena faktor ekonomi.
“Menurut keterangan sang suami, mereka ini sedang terlilit utang puluhan juta. Korban merasa tidak kuat akibat ditagih terus-menerus. Bahkan dari hasil otopsi juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi, ini murni bunuh diri,” ujar AKP Bahtiar Tanjung.
Meninggalnya Purwanti menghebohkan warga sekitar lantaran ia tidak mengenakan sehelaian pakaian. Namun, tetangga korban yang rumahnya berdampingan dan tidak mau namanya disebutkan justru memberikan keterangan lain.
“Menurut saya, dia bertahan hidup dengan suaminya sudah bisa disebut kuat. Selama ini, Pur sering dihajar. Bahkan kalau ketahuan berbicara dengan saya padahal dia menjemur pakaian, itu sudah diseret ke dalam rumahnya. Apalagi kalau pagi-pagi dan tidak membuat kopi. Pur jadi bulan-bulanan. Jadi, kalau dia bunuh diri karena utang, saya kira bukan itu penyebab utamanya. Tapi, karena sikap suaminya yang mau menang sendiri dan apa-apa harus dituruti. Termasuk memaksa istrinya hubungan badan sebelum akhirnya Pur gantung diri.”
Saat ini, jenazah Purwanti telah disemayamkan di pemakaman umum. Sementara Bahrus sang suami menolak memberi keterangan kepada wartawan. (ega/rad)
Kau lihat bagaimana tetanggamu bercerita, Pur? Keterangannya sungguh membuatku ngilu. Apalagi sekarang aku tidak tahu bagaimana cara menyapamu kembali. Mungkin lewat desau angin yang sepertegak badannya menghempaskan sisa air payau hingga menjadikan usiamu kian kemarau, doa dan salamku bisa diterima di alam sana. Ah, Pur. Sungguh, duduk di atas Geladak Gede sembari memandangi kapal Vietnam yang tengah menurunkan bahan pupuk urea, aku teringat akan perkenalan kita yang berawal dari media sosial.
Kita saling bertukar cerita. Aku dengan kegelisahan sebagai nelayan, sementara engkau tentang tembakau. Beruntunglah sehari usai kau menikah, aku meminta alamat rumahmu sebagai tempat berkirim kabar lantaran kau cerita, kalau suamimu melarangmu memegang gawai.
Tapi sekarang Pur, jangankan lewat surat, lewat angin saja aku tak lagi tahu bagaimana cara menyapamu. Kau tahu, Pur, saat ini, aku memang duduk di ujung dermaga. Namun, pandanganku jauh melewati utara Madura. Semalam Pak Lik menemuiku untuk ketujuh kalinya. Kedatangannya nyaris sama, yakni seputar nama lelaki yang baiknya aku terima untuk kawin lagi.
“Kau ini rondo, Alinda! Janda! Tak baik melaut seorang diri.”
“Sejak kapan laut berjenis kelamin, Pak Lik?”
“Bah! Sejak kapan pula kau berani melawan orangtua?”
Kalau bukan adab yang mesti dijunjung, sudah sepatutnya lelaki ringkih ini aku terjang agar giginya yang telah tanggal kian bercopotan.
“Mimpimu terlalu tinggi. Jangan harap kau dapat bantuan kapal yang hanya diperuntukkan untuk lelaki. Dan ingat, aku sudah menjodohkanmu dengan seseorang.”
Pak Lik menaruh foto seorang lelaki di atas meja. Ia tak mengutarakan sepatah kata saat berlalu keluar. Namun, sesampainya di pintu, ia terdiam sejenak.
“Berhentilah melaut!” katanya tanpa balik badan. “Wilmar di sebelah Stasiun Indro tengah mencari orang lokal. Bekerjalah di sana alih-alih berbantal ombak dan berselimut angin.”
Itulah yang Pak Lik katakan semalam, Pur. Selain menerima pinangan orang tanpa persetujuanku, ia juga memintaku bekerja di pabrik industri yang keberadaannya nyaris aku rutuki. Mungkin nasib kita tak beda jauh, Pur. Kau kehilangan kenangan menanam tembakau bersama ibumu lantaran sawah dan gumuk di Jember berubah wujud menjadi perumahan, sementara aku di Gresik sini kehilangan kenangan bersama Bapak lantaran tepi laut yang dulunya tempatku bermain, kini telah beralih menjadi pabrik industri.
Di sini, Pur, di tempatku duduk sekarang ini, dulunya bukan dermaga, melainkan lautan tempat di mana datang dan perginya nelayan berjarak dekat dengan kematian. Apalagi pabrik Petrokimia, Pur. Tak seluas sekarang, dan tak memakan tempatku menyulam kenangan.
Aku masih ingat betul, saat Bapak mengajakku melaut. Kala itu, usiaku lima belas tahun. Angin cukup kencang saat kapal meninggalkan tempatku berdiam diri sekarang. Bapak cukup awas mengamati sekitar. Ditemani sebatang rokok, ia tatap laut dalam-dalam.
“Tak ada ikan di sini. Ayo, ke Karang Jamuang!” katanya sembari mengangkat jaring.
Aku amat penasaran, bagaimana Bapak bisa tahu jika tak ada ikan di sekitaran kapal padahal baru saja ia melempar perangkap ikan ke tengah lautan. Barangkali mendapatiku terdiam, Bapak tersenyum seraya mengusap ubun-ubun.
“Kalau kita bersahabat dengan alam, mereka akan beri petunjuk, Nduk. Belajarlah mengamati sekitar.”
Meski tak paham petunjuk apa yang dimaksud Bapak sampai-sampai ia menarik kembali jaring ke atas kapal, aku mengiakan ucapan Bapak. Terlebih Bapak berseru lantang manakala mendapati kumpulan awan yang menggumpal kecil-kecil di langit tak jauh dari kapal.
Ia lekas-lekas membelokkan arah laju kemudi demi mendekati pertanda alam itu. Aku amat terpana menyaksikan langit yang begitu lapang di perairan antara Gresik dan Madura. Manakala kapal berada dekat dengan awan-awan yang seakan berserakan, dan arus laut terasa begitu tenang, Bapak melempar jaring ke tengah laut.
Sembari menunggu buruan terjerat, Bapak menyodorkan secangkir kopi. Berdua kami saling menyeruput ditemani gemigil angin malam. Barulah saat alat tangkap itu bergerak liar, Bapak memintaku menarik jaring kuat-kuat. Tarikan ini terasa sangat berat. Tak pernah aku temui tarikan semacam ini sebelumnya.
Ketika alat penangkap itu mulai mendekati permukaan, Bapak memekik bahagia. Ikan-ikan kerapu terjebak di antara simpul tali temali. Kuakui, tangkapan kali ini melebihi perkiraan. Ikan-ikan yang terangkat itu, segera Bapak taruh ke dalam kotak berisi es batu.
“Kalau begini terus tangkapan kita, Nduk,” ujar Bapak. “Kau bisa sekolah sampai ke Eropa. Nanti kau bisa jadi pelaut tangguh seperti nenek moyang kita.”
Aku cekikikan mendengar seloroh Bapak. Kendati begitu, kuakui mengamini doanya sebab Bapak sendiri sejatinya seorang pelaut. Dulunya Bapak adalah anak buah kapal asing yang sering berlabuh di dekat dermaga. Di sana, Bapak bekerja sebagai pengangkut muatan dan terpaksa berhenti saat terjadi kecelakaan kerja.
“Memangnya apa beda nelayan dan pelaut, Pak?”
Sembari memindahkan kerapu-kerapu ke dalam kotak, Bapak tersenyum.
“Nelayan itu menangkap ikan. Seperti kita ini, Nduk. Tapi, kalau pelaut, kau bisa mengemudikan kapal dan bisa berlayar ke belahan bumi mana saja. Karenanya, sekolah pelayaran yang tinggi. Kelak kau akan melihat indahnya dunia.”
Sayangnya, Pur, Bapak keburu pergi. Sepekan usai tangkapan besar itu, Bapak ditelan laut. Mayatnya ditemukan di dekat Kamal, Madura. Sejak itu, aku diasuh Pak Lik dan terpaksa menerima pinangan seorang lelaki yang ternyata bernasib sama seperti Bapak, yakni mati di laut. Satu-satunya yang aku miliki sekarang adalah kapal peninggalan Bapak yang dulu berhasil ditarik ke sini, dan diperbaiki atas nama bantuan kepada nelayan.
Kapal itulah yang aku gunakan untuk berlayar. Kapal ini pula yang membuatku tak bisa menjangkau utara Madura. Kau tahu, Pur, sejak pabrik industri menyeruak di sepanjang pesisir Gresik, dan keberadaannya terus memakan laut hingga meniadakan pantai, para nelayan seperti aku mesti berlayar jauh sampai ke Bawean. Tapi, kapalku terlalu kecil demi menyeimbangi sapuan ombak yang amat terjal. Belum lagi biaya solar yang kian meninggi. Ah, barangkali benar katamu, Pur, kalau lahir sebagai perempuan harus siap menerima takdir pincang bertubi-tubi.
Saat ini, Pur, para nelayan menerima bantuan kapal anyar yang kapasitas mesinnya lebih besar. Syaratnya, di kolom KTP mereka mesti berstatus nelayan. Sementara aku, Pur, status pekerjaanku tertulis Ibu Rumah Tangga meski aku seorang nelayan. Saat aku mengurus ke petugas desa, mereka justru tertawa. Katanya, sejak kapan nelayan perempuan diakui negara?
“Mestinya kalian paham, kita pernah dipimpin syahbandar perempuan pertama yang diakui Majapahit. Kalau kalian tak percaya, aku bisa mengantar kalian menuju Kebungson, tempat di mana Nyai Ageng Pinatih disemayamkan,” kataku saat mendapati petugas memintaku pulang.
“Bah! Kau mengajari aku sejarah? Kau itu perempuan. Jangan menyalahi kodrat!” teriak seorang lelaki berbaju putih.
“Aku tak mengajarimu!” ujarku yang tak sudi menatap lelaki itu. “Aku hanya mau, pemangku sepertimu menolak reklamasi sebab nelayan mesti berlayar lebih jauh sampai utara Madura. Bukan duduk manis menikmati kopi lantaran tiap bulan menerima kucuran uang dari pabrik industri.”
Lelaki itu tetiba berdiri. Ia ditahan seorang kawannya, namun tak menggubris. Muka lelaki itu merah padam saat berjalan mendekat dan berbisik di telinga.
“Baiknya kau belajar lagi, kalau perempuan takkan pernah setara dengan lelaki. Apalagi kodrat janda sepertimu. Mestinya kau cukup duduk mengangkang di atas ranjang, memperlihatkan lubang peranakan yang kering kerontang sebab terlalu lama tak disesapi batang lelaki.”
Kau tahu, Pur. Lelaki itu yang fotonya disodorkan Pak Lik semalam dan pernikahannya akan dilangsungkan sejam lagi. Tapi, kau tenanglah di alam sana. Di balik kutang yang kukenakan sekarang, ada sebilah belati yang sudah kuasah siang tadi.
Jember, 15 November 2023
14.12 WIB
Nurillah Achmad. Seusai menyantri di TMI Putri Al-Amien Prenduan Sumenep, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada tahun 2019, terpilih sebagai Emerging Writer of Ubud Writers & Readers Festival (UWRF). Novel terbarunya berjudul Berapa Jarak antara Luka dan Rumahmu? (Elex Media Komputindo, 2023). Saat ini tinggal di Jember dan aktif di komunitas Puan Menulis.
Residensi Literatutur mengundang 18 Penulis di Indonesia untuk diundang ke Gresik dalam upaya melakukan pembacaan, penggalian ide, dan menemukan gagasan atau kemungkinan lain yang kemudian dituangkan dalam cerita pendek. Residensi ini diadakan oleh Yayasan Gang Sebelah yang didukung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Gang Sebelah
Yayasan Gang Sebelah didirikan pada Tahun 2017, sebagai bentuk upaya dalam melakukan penelitian, pengarsipan dan pengembangan Kebudayaan.