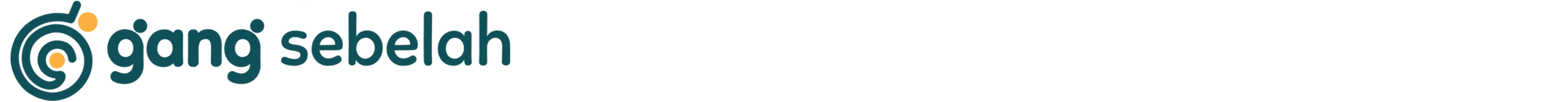Apakah setiap gagasan harus dicintai? apakah setiap keputusan yang dibuat oleh orang yang kita cintai lantas harus kita terima agar hatinya tak tersakiti?
Sepanjang malam aku memikirkannya tiada henti. Mak dan Bapak adalah orang yang paling kuhormati, mereka berdua adalah surga bagiku sebagai anak pertama yang disayanginya bagai anugerah ilahi. Mereka sendiri yang mengatakan padaku kalau aku adalah kekasih hatinya, rejeki pertama dalam perjalanan bahtera rumah tangganya, juga permata hati ketika badai kehidupan melanda keduanya. Aku adalah pertahanan paling solid yang menemani getirnya perjalanan mereka, segala hal akan dikorbankan demi kebaikan hidup yang harus aku terima.
Selama ini aku selalu menerima semua keputusan yang Bapak berikan dan pantang membuatnya kecewa. Tetapi keputusannya pagi itu membuatku bergeming tak seperti biasanya. Ia memutuskan perjalanan hidup kami sepihak tanpa aba-aba, bukan denganku, tetapi dengan Mak sebagai pasangan hidupnya. Bapak menjual seluruh warisan sawah dari almarhum Eyang Kung dan akan mengajak kami pindah ke tempat baru yang bahkan ia sendiri pun belum tahu keadaannya. Mak yang tengah hamil mudah tiba-tiba pingsan siang itu usai menerima kabar dari paman Badri, adik tertua Bapak.
Tanganku bergetar menyodorkan minuman untuk Mak yang tengah mengerjapkan matanya. Paman Badri membenarkan letak kepalanya agar Mak bisa minum seteguk air yang sudah kuberikan.
“Kipasi, Nduk,” paman memberiku isyarat dengan kedua tangannya.
“Mak gak lapo-lapo kan, man?,” tanyaku khawatir.
“Gak, Nduk, cuma kaget. Nanti lek bapakmu teko gak usah takon, menengo wae,” paman sekali lagi memberi isyarat dengan jari telunjuk di bibirnya. Aku hanya mengangguk pelan tanpa penolakan.
Sejak hari itu aku tak punya pilihan lain selain menuruti kemauan bapak. Pada akhirnya kami pindah ke desa yang lebih sepi dari sebelumnya, lebih tak berpenghuni, tetapi sepanjang jauh mata memandang, desa ini lebih padang tanpa banyak pepohonan sebab ketika kalian berdiri di tengahnya akan melihat seluruhnya adalah perairan pertambakan. Desa yang kata bapak penuh harapan, entah harapan gelap atau terang. Aku tak tahu betul bagaimana masa depan membawa kehidupan kami berempat, oh tidak, hanya bertiga sebab adik kecilku yang sedang dalam kandungan Mak tidak sempat lahir ke dunia.
Sebelas tahun berlalu, sepanjang itu kepindahan kami menjadi perjalanan baru. Aku tetap tumbuh penuh cinta kasih, hanya saja semakin banyak waktu yang kuhabiskan sendiri. Bapak nyambut di tempat juragan tambak kaya raya sebagai Pandega atau Pendego sedangkan Mak membantu berjualan ikan di pasar desa, dan aku tetap menjadi satu-satunya anugerah dalam hidup mereka.
“Kau sudah melebihi kompeni saja, menjajah diri sendiri tanpa perantara,” suara itu terdengar seperti sebuah sindiran keras untuknya yang sedang tak berhenti mengetik sepanjang siang ini. Kalau saja tak ada waktu menoleh mengambil minuman mungkin telingaku sama sekali tak mendengarkan sebab sedang konsentrasi penuh. Ini akhir tahunku menjalani perkuliahan, ada banyak tugas yang harus diselesaikan.
“Maksudnya bagaimana?”
“Kompeni menjajah ada objeknya, negara kita, lah lihat dirimu, sudah yang menjajah diri sendiri yang dijajah diri sendiri pula.”
“Bukan menjajah, Din. Aku hanya sedang berusaha menyelesaikan tugasku. ”
“Ini bukan kamu yang biasanya, Un. Kamu bukan orang yang seperti ini. Ayolah…”
Aku, Seruni, gadis kecil yang kini tumbuh berkulit kuning langsat, tinggi, berkacamata dan bertubuh kurus ini sedang merenungi perkataan sahabatku siang tadi. Tidak bisa dipungkiri, dalam satu minggu ini aku banyak menghabiskan waktu untuk menyendiri di pojok kampus yang sudah empat tahun kuhuni. Hari-hariku penuh ambisi, misi hidupku harus terjaga tanpa boleh ada yang menggoyahkanku. Sebab aku satu-satunya harapan orang tua, meski ada satu hal yang membuatku ingin memberontak sejadi-jadinya, persis beberapa tahun yang lalu.
***
Gerimis pertama yang jatuh di balik jendela masih belum berhenti sejak semalam. Rintiknya jatuh perlahan mengundang bau petrichor yang dirindukan banyak orang. Aku teringat cerita di desa, ketika hujan pertama datang anak-anak tidak boleh bermain hujan-hujanan sebab hujan pertama katanya bisa mengundang penyakit, tapi setelahnya hujan kedua ketiga dan seterusnya mereka boleh bermain air hujan sepuasnya. Kali ini aku hanya menghabiskan waktu di dalam kamar sambil mengamati lamat-lamat dunia luar di balik jendela kamar yang tepat menghadap jalan raya utama kota ini. Kota sejuta cerita, kota segala sejarah. Kota yang jika engkau ingin menulisnya tak akan habis cerita tetapi justru bertambah.
Ddrrtt….ddrrttt…
Bunyi getaran handphone dari atas meja belajarku membangunkan lamunan. Aku beranjak tapi tak langsung mengangkat panggilan telepon itu. kulihat dengan malas nama yang tertera di layar, laki-laki yang beberapa bulan ini mengganggu pikiranku. Mengganggu dalam arti yang sebenarnya, bahkan bisa dibilang mengganggu minat hidupku. Aku teringat sudah berkali-kali mendapatkan nasehat keluarga dan orang sekitar, bahwa jangan terlalu membenci seseorang, bisa jadi nanti dia jadi jodohmu. Setiap kali mengingat ucapan orang-orang itu aku hanya bisa menghela nafas panjang dan membuangnya perlahan untuk menenangkan dirinya.
“Lapo, cak?”
“Kee’po kabare, Un, kok ga pernah ngabari?”
“Apik, lagi sibuk kuliah”
“Kapan liburan? opo tak sambangi merono?”
“Gak usah. Aku sek suwe liburane, kapan-kapan ae ketemu ne, cak”
Aku tak mau banyak bicara, kali ini ingin benar-benar memperdengarkan ketidakpedulianku. Berharap laki-laki di seberang sana mengerti bahwa aku tak menyukai perjodohan ini. Aku masih ingin mencari banyak hal, masih ingin belajar banyak hal pula. Namun di luar itu semua, sejujurnya ada seseorang yang mengisi hatiku.
“Boleh gak si, Din, kita ke makam-makam dan berdoa minta biar jodoh kita jangan dia,” tanyaku pada Dinda suatu siang di parkiran kampus, kami hendak pergi berdua menyusuri kota karena jam kuliah yang kosong. Ini seperti jadwal rutin kami setiap kali ada waktu. Kebetulan Dinda hanya bisa diganggu hari itu, kami berdua sibuk masing-masing. Dinda sibuk bekerja di toko roti ketika tidak kuliah, begitu juga denganku yang sedang merintis usaha berjualan.
“Ya minta saja, tapi jangan sama mbah walinya, minta tu sama Allah tapi lewat perantara mbah wali,” Dinda tahu betul kegelisahanku. Sebagai dua orang yang lahir di tempat dan kultur berbeda, bisa dibilang kami menjadi sedekat ini karena itu semua. Ia yang lahir dari keluarga yang sudah maju, aku pernah menemui kedua orang tuanya yang sangat menyenangkan, aku lahir dari desa dengan seorang bapak yang keras kepala dan ibu yang selalu mengalah.
“Ya tahu, tapi maksudku niat permintaannya itu loh. Biasanya orang kalau ziarah itu doanya minta jodoh, nek aku minta dibelokkan jodoh”
“Wes ta, gak usah dipikir nemen-nemen, sek suwi. Jare bapakku ga ilok ndisiki pengeran, ojo sok tahu, ayok budal ke makam Nyai Ageng Pinatih,” kebiasaan Dinda adalah serius menasehati tanpa mau menatap raut wajahku yang sudah manyun melihatnya sibuk berbenah dan memakaikan helm di kepalaku semaunya.
“Un, kata kuncen makam Nyi Ageng Pinatih ini tempat orang berdoa meminta banyak perkara. Doa yang banyak di sini,” Dinda berbisik sambil menggandeng tanganku untuk masuk ke dalam area makam sesampainya di depan gapura. Ia tak ikut duduk tetapi memberiku isyarat agar segera duduk dan membaca ayat-ayat suci al-Qur’an seperti peziarah lain yang tengah khusyu’ berdoa di samping kanan kiriku.
“Makam Nyai Ageng Pinatih ini banyak dikunjungi orang untuk meminta hajatnya di sini. Banyak yang meminta jodoh, bukan hanya jodoh, tetapi banyak juga saudagar yang ke sini untuk berdoa agar usahanya dilancarkan dan sebagainya. Karena beliau ini sangat terkenal sebagai seorang saudagar sukses, bahkan yang ke sini bukan hanya orang muslim. Pernah ada peziarah hindu dari Bali yang ke sini, sebab katanya mereka mau berterimakasih pada beliau karena sudah mengajarkan perdagangan…”
Kami berdua mengangguk pelan dari belakang usai mendengarkan keterangan juru kunci makam yang menjelaskan di depan beberapa anak muda yang memakai pakaian serupa, entah mahasiswa seperti kami atau bukan, yang jelas mereka rombongan dan terlihat mewawancarai juru kunci makam. Dinda menyenggol lengan kiriku sambil meyakinkan, “Bener kan?.”
Nyai Ageng Pinatih yang kutahu adalah nama besar yang merepresentasikan perempuan penuh dedikasi dalam perjalanan sejarah Islam kota ini. Ia adalah ibu angkat Sunan Giri, ulama besar kota ini pada masa dahulu, penyebaran Islam di seluruh Nusantara ini tak luput dari namanya sebagai gurunya para wali. Meski bukan ibu kandung, namun peran Nyai Ageng Pinatih sangat berjasa karena telah memberikan pendidikan terbaik bagi putra angkatnya. Ia digambarkan sebagai mar’atus sholihah, perempuan sholihah, yang cantik rupawan sebab ia juga merupakan keturunan bangsawan dari Samboja. Sayangnya kisah tentang pasangannya ketika beliau sudah sampai di Gresik tidak pernah diceritakan dalam sejarah.
“Kalau saudagar yang kesini wajar si, Din. Sepak terjang beliau sebagai syahbandar tak diragukan. Tapi kalau minta jodoh…beliau sampai akhir hayatnya diceritakan tidak bersama pasangannya,” Dinda memelototiku dan mengisyaratkan untuk diam dengan meletakkan jari di mulutnya.
***
“Un, berdoa saja gak cukup, usaha yang lain lah,” goda Dinda sore itu di tengah perjalanan safari religi kami berdua menyusuri kota Gresik. Kami duduk berdua di tepi situs bukit Giri Kedaton sembari menyisir kota dari ketinggian. Bukit yang menjadi saksi perjuangan dakwah sang alim.
“Sunan Giri kekuasaannya hebat juga ya, Din?”
“Gak usah mengalihkan pembicaraan, curhatanmu mau durung mari. Sopo mau seng katamu mbok karepi?,” Dinda rupanya mengejar pernyataanku. Kupikir ia hanya konsentrasi menyetir sepeda motor sepanjang perjalanan tadi, namun ternyata dia mendengar semua curahan hatiku yang sebenarnya.
Beberapa bulan yang lalu aku sempat berkunjung ke toko roti tempat Dinda bekerja. Sambil menunggunya untuk menemuiku, aku sengaja duduk di salah satu sudut cafe di seberang jalan. Hari itu hujan deras, seorang pemuda berkemeja rapi dan tengah menenteng tas di bahunya tiba-tiba masuk ke dalam cafe tempatku duduk untuk berteduh dari derasnya hujan sore itu. Berkali-kali ia menoleh ke kanan dan kiri sebab cafe lumayan ramai di sore menjelang malam, tapi rupanya ia tak menemukan kursi kosong selain di depanku. Sambil tersenyum ia meminta ijin untuk duduk di hadapanku, aku mengangguk.
“Suka baca buku ya?,” ini serupa perjumpaan klasik untukku yang sering membaca novel-novel lawas karya Motinggo Boesje. Dari perjumpaan itu kami berkenalan dan menanyakan profesi masing-masing. Rupanya ia bukan anak kota sini, ia sedang berlibur dan menginap di salah satu rumah saudaranya dan sengaja berkeliling kota tua bandar Grisse untuk mencari inspirasi di tengah liburannya. Ia kuliah jurusan arsitektur di salah satu universitas Jakarta. Usai pertemuan itu aku sama sekali tak tahu bagaimana cara untuk menemuinya kembali, kecuali hari ini…
“Din, kata bude kamu disuruh segera pulang…,” aku sontak menoleh mendengar suara yang sama sekali tak asing. Pemuda itu tiba-tiba berdiri di belakang kami dengan nafas yang masih terengah-engah setelah menaiki tangga. Aku mengernyitkan dahi dan memasang muka penuh tanda tanya, sama sekali tak tahu maksud semua ini.
“Mas Sihab, sepupuku, anak arsitektur yang kemarin kenalan sama kamu kan…” Dinda tersenyum menatapku. Ia rupanya melihat kami duduk berhadapan dari sebrang toko roti tempatnya bekerja namun tak pernah menceritakannya kepadaku sama sekali.
“Jadi…berdoanya yang khusyu ya, mbak. Semoga terkabul apa yang kau minta di makam tadi. Aku pulang dulu, bentar lagi ibuku pidato kebangsaan kalau aku telat pulangnya, bye.”
“Din…terus aku ngko moleh karo sopo?”
“Lah iku…,” ia berlalu sambil melambaikan tangan tanpa menoleh padaku sama sekali. Asem. Pasti ini sudah dirancangnya jauh-jauh hari, entah sejak kapan, yang jelas ia terlihat puas menertawakan kepanikanku.
Eva Maulidiyah Bichrisyea Liberty adalah penulis cerpen, esai, dan bagian dari penulis muda TTS Kompas. Pernah menempuh pendidikan S1 jurusan Sejarah Kebudayaan Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak duduk di bangku Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin, Gresik, sudah tertarik dengan dunia kepenulisan.
Gang Sebelah
Yayasan Gang Sebelah didirikan pada Tahun 2017, sebagai bentuk upaya dalam melakukan penelitian, pengarsipan dan pengembangan Kebudayaan.