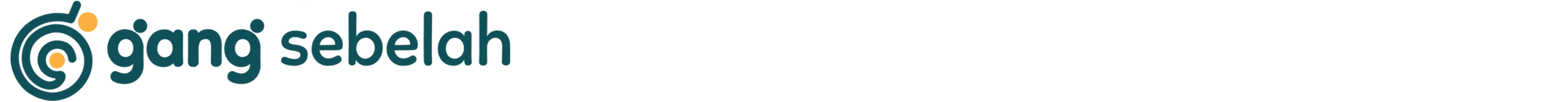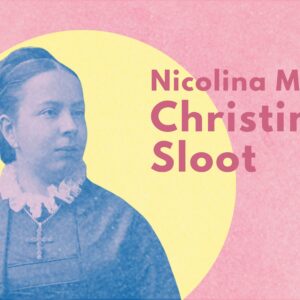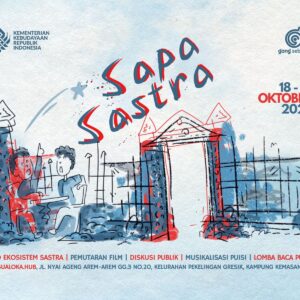Malam, 6 September 2025, di kedai kopi Gresiknesia. Percakapan tentang “Menyisir Jalan kebudayaan dari Pesisir,” berlangsung hangat—aroma beragam minum dan kudapan bercampur dengan ide-ide yang menyala. Menghadirkan Ismal Muntaha dari Jatiwangi Art Factory dan Hamdani dari kolektif Pasir Putih Lombok Utara untuk menimbang arah dan strategi kebudayaan hari ini.
Ismal menegaskan, bahwa warga adalah pemilik kebudayaan. “Dari tangan mereka tradisi lahir, dari kehidupan sehari-hari ia tumbuh. Kebudayaan bukan menara gading, bukan pula seremoni yang beku, melainkan napas bersama yang meleburkan sekat.”
Ia kemudian mencontohkan Jatiwangi Art Factory dengan Rampak Genteng—ritual tanah yang dilakukan kolosal, melibatkan seluruh warga—hingga prosesi pernikahan simbolik antara Bappenas dan Kemendikbud, sebagai janji menjaga tanah.
Imajinasi lokal menjelma aksi nyata. Dari situ lahir pula Mother Bank, yakni gerakan ibu-ibu bermusik yang menumbuhkan simpan-pinjam warga. Bukti bahwa jalan kebudayaan bisa menjadi jalan ekonomi, menghidupi jiwa sekaligus menggerakkan tubuh sosial.
Apa yang dilakukan Ismal bersama Jatiwangi Art Factory memperlihatkan bagaimana imajinasi kebudayaan bisa menempuh jalan yang tidak biasa. Rampak Genteng menjadikan tanah—yang lazimnya dipandang benda mati—sebagai sumber bunyi ritmis yang menggerakkan kolektif. Menikahkan secara simbolik Bappenas–Kemendikbud, menggeser prosesi formal negara ke dalam ruang budaya, mengubah institusi menjadi simbol komitmen menjaga tanah. Sementara Mother Bank memperlihatkan bagaimana musik ibu-ibu dapat menjadi pintu masuk praktik ekonomi.
Dari sini tampak bahwa kebudayaan bukan sekadar melestarikan warisan, melainkan mesin produksi imajinasi sosial. Ia bisa menjadi ruang politik, ekonomi, spiritual, sekaligus artistik—semuanya cair.
Sementara Hamdani, mengisahkan jalan Pasir Putih Lombok Utara: jalan kebudayaan dari pesisir. Kolektif ini dikenal dengan Bangsal Menggawe, festival rakyat tahunan di Pelabuhan Bangsal yang mempertemukan seniman dan warga dalam ruang bersama penuh perayaan sekaligus refleksi.
Mereka juga melahirkan inovasi senam rudat—adaptasi kontemporer dari tarian tradisional rudat—yang kini digemari ibu-ibu, menjadi praktik kebersamaan baru sekaligus cara membangkitkan kebanggaan budaya lokal. Dari dua praktik ini terlihat bahwa jalan kebudayaan pesisir bukan sekadar menjaga bentuk lama, melainkan menyalakan kembali denyutnya agar tetap relevan.

Sedangkan Gresik menyimpan jejak leluhur yang kaya. Ada Sunan Giri, yang mendirikan pesantren di dataran tinggi dan menjadikan tembang dolanan sebagai sarana dakwah; Nyai Ageng Pinatih, perempuan niaga yang mengatur persinggahan dari laut. Bermunculan pula maestro seni seperti Masmundari, pelukis lampion legendaris yang karya-karyanya menembus lintas generasi, dan Mbah Mat Kauli, pelestari tembang macapat yang memberi napas pada tradisi lisan Jawa di Gresik.
Dari laut yang menumbuhkan keberanian, dari tanah menanamkan kesabaran, dan dari industri yang melatih kerja keras, leluhur meninggalkan warisan yang tak lekang. Potensi spiritual Gresik pun terasa membuncah. Fenomena menziarahi makam para Sunan, lembaga pengajian, hingga praktik baca-tulis Al-Qur’an yang hidup di tengah warga.
Semua itu menyimpan daya spiritual yang kuat—daya yang menautkan iman, kebersamaan, dan daya cipta. Bila diolah dengan imajinasi, daya spiritual ini dapat membuka jalan kebudayaan baru, di mana ritual keagamaan bertransformasi menjadi energi kolektif warga.
Namun warisan ini sekaligus tantangan. Ia bisa menjadi sumber daya, tetapi juga beku sebagai nostalgia bila tak ditafsir ulang. Gresik yang memiliki modal kebudayaan ciptaan leluhur sesungguhnya menyimpan sumber tak habis digali. Kita perlu mempelajari pola-pola kerjanya untuk mencipta mitos kita sendiri—agar sejarah tidak berhenti sebagai arsip, melainkan terus hidup sebagai arah dan kompas masa depan.
Kebudayaan adalah energi pertemuan, berdetak di dada warga, menjadi inspirasi dan penopang kehidupan bersama. Selama ia dihidupi, ia tetap menjadi jalan—jalan tanah, jalan pesisir, jalan kehidupan, jalan kebudayaan.
Lebih penting lagi adalah memiliki imajinasi yang mampu merespon potensi dan persoalan menjadi tidak biasa—imajinasi yang lahir dari keberanian membaca ulang warisan, sekaligus keberanian mencipta jalan baru.
Di sinilah Gresiknesia menemukan maknanya. Kehadiran Ismal dan Hamdani bukan semata forum dialog, melainkan ikhtiar mempertemukan tanah dan pesisir, imajinasi dan warisan, ekonomi dan spiritualitas. Dari ruang kecil berwujud kedai kopi, jalan kebudayaan ditenun kembali—bukan untuk dikenang semata, tetapi untuk ditapaki bersama.
Gang Sebelah
Yayasan Gang Sebelah didirikan pada Tahun 2017, sebagai bentuk upaya dalam melakukan penelitian, pengarsipan dan pengembangan Kebudayaan.