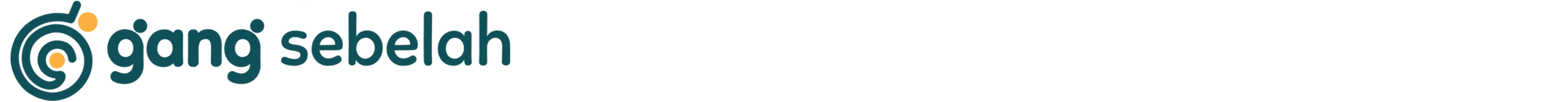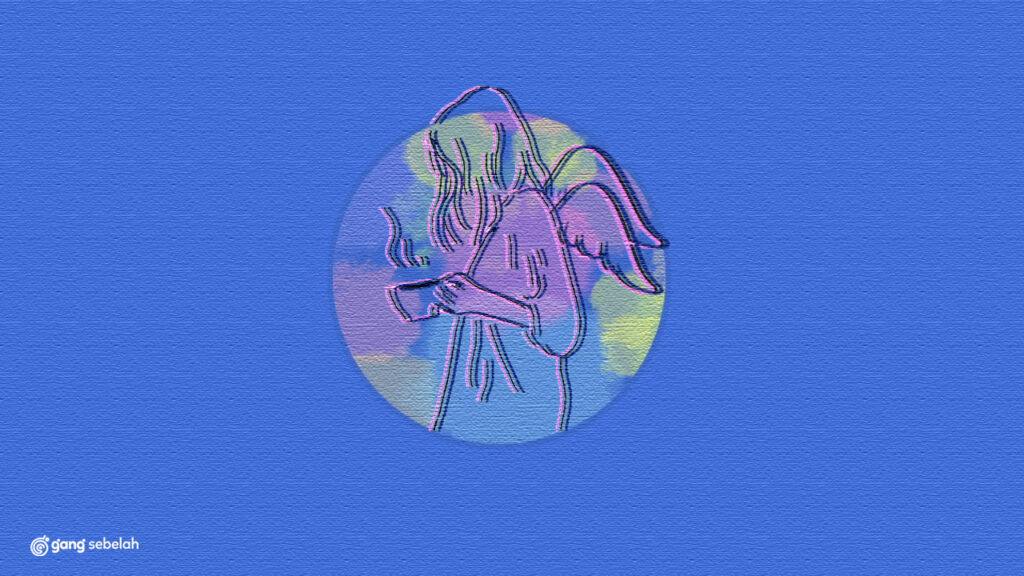
pertemuan di suatu hari, membuatku ingin mengenal lelaki itu lebih jauh. Kisahnya membuatku percaya kepada sebuah istilah klise: ‘Cinta tak butuh alasan’. Ia masih berlaku dalam kehidupan yang kian menuntut banyak syarat ini. Kiat-kiat mencintai dengan benar telah dia tunjukkan. Ya! Aku hanya butuh satu hari untuk mempercayainya, sedikit kusayangkan kenapa Tuhan tidak membuka tabir itu sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di desa terpencil ini?
* * *
Sudah berjalan tiga minggu pengabdian. Aku masih ingat betapa warga antusias menyambut kedatangan kami. Dengan rela mereka membawakan tetek bengek perlengkapan dan menyuguhkan berbagai makanan khas pedesaan yang begitu jarang bahkan hampir tak pernah kami jumpai di kota. Kalau tidak salah namanya clorot, grontol jagung, jadah, cenil, dan masih banyak lagi.
Sungguh, wajah ramah Indonesia masih mereka miliki. Jujur saja, di kota aku banyak mendapati orang-orang kehilangan senyum. Kesibukan dan hiruk-pikuk membuat suasana selalu tampak terburu-buru. Terkesan tidak ada waktu untuk peduli dengan orang lain.
Satu sisi aku sangat bahagia bisa mengabdi di desa nan tenteram ini. Pepohonan menghias di sepanjang jalan. Sawah dan ladang terhampar bak permadani yang sengaja Allah gelar. Udaranya? Jangan tanya! Tak cukup sekali hirup, sangat segar.
Di sisi lain aku harus rela kehilangan followers Instagramku karena beberapa minggu ini jarang update snapgram. Sinyal di desa tak menjanjikan. Entah, apakah pembangunan Indonesia dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi belum sanggup menjangkau salah satu pelosok di negeri ini. Ah, masyarakat di desa tempatku mengabdi sungguh polos. Tidak adakah yang ingin mengenal dunia maya? Atau sekadar membaca broadcast hoaks di WA? Hm… otak mereka sungguh masih perawan, hehe.
Namaku Batari, mahasiswi semester tujuh yang sedang menikmati masa-masa pengabdian. Apalagi setelah mengenal seorang marbut musala yang biasa kami panggil Mbah Sono. Selain marbut, beliau juga menjadi muazin.
Ya, berawal dari mendengar azan di hari pertama pengabdian. Suaranya membuatku dan kelima teman yang lain tertawa di basecamp. Ah, itulah dosa yang pertama kali kami lakukan di desa ini. Menertawakan suara muazin yang kedengaran seperti orang yang tercekik. Bahkan sebelum bertemu pun, kami sudah tahu pemilik suara itu sudah sepuh.
“Kasihan muazin ini, napasnya sudah pendek-pendek. Semoga stok napasnya masih cukup sampai azan selesai,hahaha…” celetuk Udin, langsung kusambut dengan gebukan maut. Aku menduga temanku itu lahir dalam keadaan mulut yang blong. Kalau bicara kadang tidak difilter dengan baik.
Hingga kami dipertemukan oleh kepala desa dengan beliau seusai salat Asar. Lelaki sepuh kira-kira berusia tujuh puluh tahunan lebih dengan sarung dan baju koko yang kumal, serta songkok miring menyambut dengan senyum ala iklan pasta gigi. Sangat percaya diri memperlihatkan giginya yang tidak lengkap dan kekuningan.
Saat itu juga Mas Ghofur menyampaikan bahwa selama pengabdian semua pekerjaan Mbah Sono bisa dilimpahkan kepada kami. Tabiat Mas Ghofur yang sopan, membuatku nyaris salah fokus kepadanya. Mimpi apa aku bisa satu kelompok dengan ketua rohis yang ‘bapak-able’ ini?
“Jadi, panjenengan hanya memantau dan salat saja, Mbah. Biar azan dan membersihkan masjid kami yang melakukan,” ujar Mas Ghofur disambut senyum ala Mbah Sono sambil manggut-manggut. Senyum yang lebih lebar dari sebelumnya, menunjukkan beliau sepakat bahkan senang karena pekerjaannya menjadi ringan.
“Alhamdulillah, Mbah bisa lebih lama bersama istri di rumah,” ucap beliau dengan wajah yang berbinar-binar.
Ya, sosok Mbah Sono mengingatkanku pada Eyang Habibie. Beliau tampak sangat mencintai istrinya. Bahkan meski di usianya yang sudah sepuh. Terkadang aku heran bagaimana seorang lelaki tua bisa mempertahankan rasa cinta kepada pasangannya? Kurasa tidak ada lagi hal menyenangkan yang bisa dilakukan sepasang kakek nenek selain melihat anak-anaknya berumah tangga dan menghasilkan cucu yang lucu-lucu. Tapi Mbah Sono tidak memilikinya. Beliau benar-benar hidup berdua dengan sang istri.
“Wah, Mbah. Istri panjenengan pasti sangat cantik ya? Sampai Mbah Sono tidak mau jauh-jauh? Kayak pengantin baru aja sih?” goda Udin, si mulut blong itu langsung kami hadiahi pelototan tajam. Tapi rupanya beliau malah tertawa dan asyik-asyik saja. Pasti kalian pernah dibuat tertawa oleh tawa seseorang kan? Duh, kalimat tanya yang membingungkan. Tapi kami memang ikutan tertawa setelah mendengar nada tawa Mbah Sono yang ada ngik–ngik–nya.
“Dia perempuan tercantik yang pernah saya temui,” seloroh Mbah Sono seketika disambut oleh cuitan Udin dan beberapa temanku yang lain. Entah kenapa aku meleleh mendengar sebaris kalimat Mbah Sono untuk sang istri. Hahaha, tidak kusangka lelaki sepuh seperti Mbah Sono rupanya punya sisi gombal juga.
Meski setiap hari kami bertemu Mbah Sono, tapi tidak pernah lama. Ada banyak program yang harus kami realisasikan di berbagai tempat di desa ini. Kami berpencar, ada yang membantu di puskesmas, posyandu, balai desa, musala, dan membersamai warga di sawah mereka.
Padahal kalau boleh jujur, aku ingin berkunjung ke rumah Mbah Sono dan bertemu istrinya. Aku ingin tahu wanita seperti apa yang bisa membuat seorang lelaki begitu mencintai dan sangat bangga memilikinya. Bahkan setiap hari, di antara begitu banyak kisah yang disampaikan Mbah Sono selalu terselip cerita tentang sang istri yang kuketahui bernama Mbah Minah tersebut. Tapi apa daya? kesibukan kami terlampau hebat sehingga selama tiga minggu mengabdi keinginan itu belum terlaksana.
“Rumah Mbah Sono dekat sini?” tanya Nisrina, salah seorang temanku. Rupanya dia juga penasaran ingin bertemu Mbah Minah yang kerap dipuji sebagai wanita tercantik itu.
“Wah, jauh. Kurang lebih satu kilometer. Harus menyebrang sungai dulu. Kalau bukan karena ingat kewajiban seorang lelaki untuk salat di masjid atau musala, Mbah lebih memilih salat di rumah dengan Minah,” jawab Mbah Sono dengan mantap.
Pemandangan yang kontras kerap kusaksikan. Di kota, puluhan masjid dibangun megah, tapi jamaahnya raib entah kemana. Sedangkan di desa ini, hanya ada sebuah musala, namun selalu penuh setiap salat lima waktu.
* * *
Azan magrib telah dikumandangkan oleh Mas Ghofur. Sungguh hebat Allah menciptakan suara indah seperti yang dimilikinya. Membuat hampir semua jamaah tertegun dan khusyuk mendengarkan. Mas Ghofur, seseorang yang diam-diam aku kagumi karena tabiatnya yang tenang. Walaupun aku sadar, seorang Batari hanya remahan rengginang di dasar stoples yang rasanya sudah tengik. Tidak ada apa-apanya dibanding ukhti-ukhti salihah yang juga mengidolakannya. Tapi sudahlah, mari kita kembali ke Mbah Sono.
Kebetulan hari ini di musala hanya ada aku, Mas Ghofur, dan Udin. Kami bertiga menunggu waktu salat Isya sembari membereskan beberapa bagian musala yang berantakan setelah anak-anak mengaji. Seperti biasa, Udin selalu menjadi manusia berisik yang membicarakan segala hal.
“Eh, Fur! Kok aku curiga ya. Jangan-jangan Mbah Sono itu tua-tua keladi?” duganya sambil sibuk meletakkan beberapa kitab ke lemari. Aku hanya meringis saja mendengarkan celotehan kawanku yang satu itu.
“Hus! Ngawur!” sergap Mas Ghofur.
“Sekarang gini deh, mana ada sih kakek-kakek yang punya cinta begitu besar kalau bukan karena istrinya cantik? Jangan-jangan nih, istri Mbah Sono itu masih ABG! Jadi Mbah Sono lengket terus.”
Kali ini aku dan Mas Ghofur tidak bisa menahan tawa. Suasana yang tadi hening mendadak gaduh gara-gara hipotesis Udin yang ngawur.
“Udin peak! Korban sinetron,” celetukku.
Kami dikejutkan oleh salam Mbah Sono. Harapanku, semoga Mbah Sono tidak mendengar pembicaraan Udin barusan. Beliau langsung bergabung merapikan beberapa jilid dan kitab, sambil sesekali membukanya dan menggeleng-geleng entah apa maksudnya.
“Jilid, Minah pernah mengajarkan saya membaca jilid seperti ini,” ujar Mbah Sono sambil menunjuk-nunjuk rangkaian huruf hijaiah sederhana pada jilid ngaji yang dipegangnya. Kami hanya menyimak pembicaraan beliau. Lagi-lagi kesan sumringah tidak bisa tertutup oleh gurat senja maupun berewok Mbah Sono yang sudah putih. Kalau bisa kubilang, beliau seperti orang yang kasmaran setiap berkisah tentang Mbah Minah. Matanya menyiratkan rasa syukur karena dianugerahi teman hidup hingga masa tuanya.
“Mbah Minah seorang guru mengaji, Mbah?” tanya Mas Ghofur menanggapi. Mbah Sono menggeleng, matanya masih lekat memandang jilid seakan-akan ada kenangan yang tersingkap dalam pikirannya.
“Dia hanya muruk ngaji saya. Walaupun sampai saat ini saya belum lancar membaca Alquran. Tapi setidaknya bisa Alpatekah berkat bidadari di rumah. Jadi kalau salat rukunnya bisa terpenuhi,” senyum kami mengembang saat Mbah Sono menyebut istrinya sebagai bidadari. Keromantisan Mbah Sono memang tidak bisa diragukan.
Keinginan untuk mengunjungi kediaman Mbah Sono semakin menggebu-gebu. Terselip janji pada diriku sendiri, sebelum masa pengabdian di desa ini berakhir aku harus menyempatkan diri bertemu Mbah Minah. Wanita yang akhir-akhir ini membuatku penasaran tentang sosoknya dan kecantikan yang ia miliki.
Jarak musala ke basecamp kami tidak begitu jauh. Tapi, dengan kondisi jalan yang terjal dan becek karena gerimis tadi sore membuat perjalanan menjadi lama. Apalagi tidak ada penerangan, membuatku harus berhati-hati agar tidak terperosok. Suasana yang sepi dan mencekam menguasai malam di desa ini. Meskipun waktu masih menunjukkan pukul delapan, tapi rumah warga sudah tertutup rapat. Hanya ada beberapa orang yang nongkrong di warung sambil meronda.
“Mas Ghofur, sebelum masa pengabdian ini usai aku mau berkunjung ke rumah Mbah Sono,” ujarku diiringi asap yang membumbung dari mulut efek udara dingin.
“Oh, kalau begitu kutemani ya?”
Aku sempat terkejut dengan penawarannya. Maksudku bercerita tadi bukan agar ditemani. Hanya izin. Minimal memberitahu. Aku hanya menghargai Mas Ghofur sebagai ketua kelompok kami. Sontak saja aku menolaknya, aku merasa bisa ke sana sendiri tanpa merepotkan orang lain. Apalagi orang tersebut Mas Ghofur.
“Jangan gitu! Medan ke rumah Mbah Sono sulit dilewati. Apalagi kamu belum pernah ke sana sebelumnya.”
Aku hanya menatap punggung Mas Ghofur. Ya, aku berada di belakangnya. Karena kami hanya jalan berdua. Udin pulang duluan gegara perutnya bermasalah.
“Mas kan juga belum pernah ke sana?” tanyaku sedikit mengeyel.
“Iya, setidaknya kalo ada apa-apa kan kamu ada temannya.”
Huft! Rasa jengkel sempat hadir tapi aku menampiknya. Mungkin benar, jalan menuju rumah Mbah Sono cukup berisiko.
* * *
Dua hari lagi pengabdian kami di desa nan indah ini berakhir. 95 persen program telah dilaksanakan dengan baik. Tidak kusangka, aku bisa hidup kurang lebih empat minggu tanpa sosial media. Semua aktivitas dunia mayaku tergantikan oleh kesibukan membantu para warga.
Menepati janjiku untuk berkunjung ke kediaman Mbah Sono sebelum kembali ke kota. Rencananya hari ini aku bersama Mas Ghofur dan Udin akan pergi ke sana pukul delapan pagi. Nisrina dan kawanku yang lain tidak bisa ikut karena ada agenda bersama warga di puskesmas.
Memang, setelah perbincangan bersama Mas Ghofur malam itu, aku memutuskan untuk tidak pergi berdua dengannya. Menghargai budaya di desa ini yang sarat akan nilai kesopanan. Selain itu, bila benar-benar berduaan, tentu sepanjang perjalanan akan terasa canggung. Mas Ghofur pasti diam bila tidak ada hal yang penting untuk dibicarakan. Tidak seru. Kalau ada Udin, suasana bisa mencair berkat leluconnya yang garing.
Sepanjang jalan kami disuguhi pohon-pohon besar, bahkan sinar matahari kesulitan menyusup di antara reranting sehingga nuansa lembab sangat terasa. Suara gemercik air sungai mengiringi perjalanan menuju rumah Mbah Sono. Dengan kondisi tubuh yang ringkih beliau tetap sanggup menaklukkan medan berat yang membahayakan hanya untuk salat berjamaah di musala.
Benar-benar luar biasa. Aku yang segar bugar saja sudah kelelahan di separuh perjalanan. Kini aku percaya sesungguhnya perjalanan terjauh bagi seorang lelaki bukanlah lintas negeri, tapi saat mereka menempuh jarak untuk mendirikan salat berjamaah dari rumah ke musala.
“Heran, kenapa dulu Mbah Sono mau membeli rumah di daerah terpencil ini sih?” gerutu Udin sambil sesekali menghindari carang di depannya.
“Mungkin hanya rumah itu yang diwariskan leluhurnya,” jawab Mas Ghofur seadanya.
Boleh jadi letak rumah Mbah Sono terpencil dari perkampungan warga. Tapi, di rumah itulah Mbah Sono hidup bersama bidadari yang sangat dia cintai. Aku membayangkan wanita yang sanggup menjadi bidadari bagi suaminya pastilah dia yang selalu menyenangkan apabila dilihat. Kalau mengingat tujuanku bertemu seorang yang luar biasa seperti Mbah Minah, kelelahan di perjalanan ini rasanya masih sanggup kutaklukkan.
Kurang lebih satu jam kami berjibaku dengan kebingungan mencari rumah Mbah Sono. Alhamdulillah, dengan mengikuti arahan yang diberikan Mbah Sono beberapa waktu lalu akhirnya sampai juga. Satu-satunya rumah tua berdiri di tengah hamparan sawah. Terdapat pula jalur-jalur pengairan di sekelilingnya.
Sebelum masuk, aku menyempatkan diri melihat para petani bahu-membahu menyiapkan sawah mereka sebelum masa panen tiba. Ah, sepertinya aku akan merindukan suasana desa sepeninggalku dari masa pengabdian.
“Semoga benar ini rumahnya. Biar gak jalan lagi, capek, Bos!!” keluh Udin. Sebenarnya aku juga mempunyai harapan yang sama, semoga kami tidak salah. Kakiku sudah menyerah.
Mas Ghofur mengetuk pintu seraya memberi salam kepada si empu rumah. Diikuti oleh aku dan Udin. Belum ada jawaban. Kami mengulang hal yang sama, dengan suara yang lebih keras.
“Waalaikumsalaam,” jawaban justru datang dari sisi kanan rumah tersebut. Senyum itu, memancar mengalahkan matahari yang kian meninggi. Menyambut kami seperti yang selalu beliau lakukan.
“Mbah Sono, alhamdulillah berarti kami tidak salah rumah,” ucap Mas Ghofur menyaliminya, kemudian kami ikuti.
“Bagaimana perjalanan kalian?” tanya Mbah Sono sembari menyilakan kami duduk di tikar yang sudah beliau siapkan di samping rumah. Kukira itu adalah kalimat retoris yang tidak memerlukan jawaban. Mbah Sono pasti sudah mengetahuinya.
“Mbah, Mbah! Kalau memilih rumah itu yang strategis-lah. Dekat dengan jalan tol kek, mal, atau setidaknya dekat sama tetangga. Posisi rumah Mbah malah dekat dengan Tuhan, bahaya sekali untuk keselamatan,” Udin nyerocos dengan kecepatan cahaya. Mbah Sono malah tertawa sampai terdengar bunyi ngik-ngik khasnya. Udin, aku urung menghajarnya karena berkat lelucon ngawur itulah suasana jadi mencair.
Setelah puas menikmati keindahan alam sambil menikmati kopi dan singkong rebus di samping rumah Mbah Sono, beliau mengajak kami masuk menemui sang istri. Rumah kayu sederhana dengan perabotan seadanya. Kukira akan ada wanita tua yang menyambut kedatangan kami dengan senyum yang menyenangkan lalu mengulurkan tangan untuk disalimi. Ternyata tidak ada siapapun, salam kami mengudara tanpa ada suara yang menjawabnya.
Mbah Sono terus mengawal kami hingga tiba di suatu ruang. Gelap. Mataku tidak bisa menangkap dengan jelas segala yang ada di kamar ini sebelum beliau membuka jendela dan membuat kami diam seketika. Napasku tercekat. Hal yang sama juga dirasakan Mas Ghofur dan Udin. Bahkan, Udin sampai membungkam hidung-mulut dengan telapak tangannya.
Sosok perempuan bertubuh kurus kering, berpipi kempot, dan mata melotot. Mungkinkah itu Mbah Minah? Sosok bidadari yang dipuji-puji Mbah Sono dalam setiap ceitanya? Kurasa benar. Jauh dari perkiraan Udin yang menebak kalau istri Mbah Sono adalah seorang wanita muda yang cantik. Justru yang kami hadapi saat ini adalah nenek-nenek tidak berdaya yang meringkuk di ranjang kayu dengan rambut putih tergelung. Jarit menutup kaki hingga permukaan dadanya.
Sungguh, tubuh itu hampir tidak berdaging. Lengannya tampak sekecil tongkat pramuka. Wanita tua dengan sorot mata sayu dalam keadaannya yang setengah sadar masih sempat melempar senyum kecil ke Mbah Sono.
“Dialah bidadari saya,” ujar Mbah Sono singkat sambil mengelus pucuk kepala Mbah Minah. Lidahku benar-benar keluh, semua bayangan tentang betapa cantik fisik Mbah Minah menguap entah kemana. Pelupukku rasanya penuh melihat dua insan di hadapanku yang tabah dengan nasib di masa tua mereka.
“Hahaha (ngik, ngik), saya tahu kalian pasti kaget kan? Tapi dia memang bidadari yang saya miliki. Wanita tercantik yang pernah saya temui. Terlepas dari kondisinya saat ini.”
Saat kami iba melihat kenyataan hidup Mbah Sono, beliau malah tertawa. Tidak menunjukkan raut kesedihan sama sekali. Aku bingung harus tertawa mendengar gelak tawa khas Mbah Sono atau meneteskan peluhku yang sudah penuh.
“Mbah Minah sakit apa? Tidak dibawa ke rumah sakit?” tanya Mas Ghofur memberanikan diri.
“Sakitnya banyak, saya lupa nama-namanya. Yang jelas Minah sudah lumpuh, tubuhnya akan tetap menekuk karena bertahun-tahun meringkuk di ranjang kayu ini. Dia juga tidak bisa bicara. Sudah usaha dibawa ke rumah sakit manapun. Tapi Minah sepertinya lebih senang berada di rumah, bersama saya menghabiskan usia berdua.”
Mbah Sono begitu tabah. Mungkinkah tebing-tebing di pegunungan ini telah mengajarkan kekuatan pada beliau?
“Bagaimana kalau Mbah Sono sedang salat ke musala?” pertanyaan brilian datang dari mulut Udin. Si mulut blong itu tiba-tiba menjadi sosok serius karena rasa penasarannya.
“Saya ke musala memenuhi panggilan-Nya, maka Dia akan menjaga Minah selagi saya tidak ada di rumah. Alhamdulillah, banyak petani di sekitar sini yang baik bersedia menyuapi Minah saat waktu makan tiba dan menemaninya beberapa saat.”
Benarlah, pertolongan Allah senantiasa mengiringi kesulitan yang Dia berikan. Menurut cerita Mbah Sono sebelum Mbah Minah sakit, beliau tipe perempuan pekerja keras dan setia. Setiap hari membantu sang suami mencari kayu di perkebunan dan hutan yang jauhnya bukan main untuk kemudian dijual.
Tiga puluh tahun yang lalu, ketika Mbah Sono dipidana karena lalai dalam pekerjaannya menjaga palang kereta api, Mbah Minah bertahan sendirian di rumah kayu ini. Seminggu sekali beliau menjenguk di lapas kota dengan membawakan makanan kesukaan Mbah Sono. Kegiatan itu terus beliau lakukan hingga masa tahanan berakhir.
“Setelah peristiwa penahanan itu, Minah mengajarkan saya ngaji jilid dan salat sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan ampun. Sampai saat ini, saya terus pergi ke musala karena tahu Minah akan meridainya. Sebelum lumpuh, dialah yang paling semangat menyiapkan segala keperluan salat saya.”
Barulah aku melihat mata Mbah Sono berkaca-kaca. Kebaikan Mbah Minah sangat membekas di hati dan ingatannya. Mungkin itulah alasan kenapa Mbah Sono mengatakan memiliki bidadari di rumah.
“Awalnya Batari mengira cinta lelaki akan sirna seiring memudarnya kecantikan seorang perempuan, Mbah,” timpalku.
“Banyak hal telah kami lalui. Minah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk menemani saya. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya, meski dalam kondisi seperti ini.”
Aku sedang tidak menonton film. Kalimat indah itu tidak keluar dari mulut Rangga, Dilan, atau pemeran utama yang masih muda dan gagah. Melainkan Mbah Sono, seorang lelaki tua yang ringkih, marbut musala, sekaligus muazin yang sempat kami tertawakan di hari pertama pengabdian.
Karena kondisinya, Mbah Minah tidak bisa menghidangkan segelas kopi untuk sang suami atau sekedar bercengkerama menghabiskan masa tua mereka di pagi dan sore hari. Tapi selama beliau sehat, hidupnya telah dipersembahkan untuk mengabdi kepada Mbah Sono.
“Tidak ada yang saya inginkan lagi saat ini, selain menjadi teman sehidup sesurga bagi Minah. Untuk kalian, cucu-cucuku, genapilah separuh agama dengan seseorang yang bisa menemanimu dalam berbagai keadaan,” nasihat beliau menutup perbincangan hari ini.
* * *
Salah satu poin Tridharma perguruan tinggi telah aku jalani, yaitu pengabdian masyarakat melalui program KKN di desa ini. Banyak hal telah aku dapatkan, salah satu hal paling berkesan adalah belajar mencintai dengan benar seperti kisah Mbah Sono dan Mbah Minah. Mereka ikhlas menerima keadaan masing-masing. Saling mencintai tanpa syarat.
Entah siapapun yang menjadi penggenapku suatu hari nanti, doa terbaik selalu aku kirimkan untuknya. Ya, dari aku. Si remahan rengginang yang mendambakan seorang pangeran mirip Mas Ghofur. Aih! Beneran Mas Ghofur juga tidak apa-apa deh,hahaha. Semoga Tuhan melihat dan malaikat mencatat.
-Paras yang rupawan ada masanya, hati yang menawan kekal selamanya-