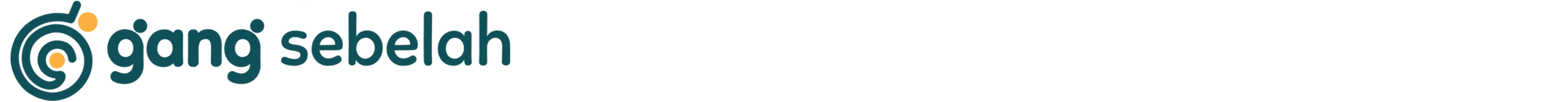Kegemaran menikmati laut membuatnya tak asing dengan kampung ini. Ia sedang menikmati berpakansi. Perjalanan sendirian mengarahkan langkahnya menuju pantai dengan air laut yang melambai, nelayan yang kerap bingung menetapkan sandaran, tetap melaut atau menjadi porter pejuang pikulan. Aroma air payau, amis ikan yang terlambat diselamatkan, juga akrab di hidungnya. Tepian muara yang sarat sampah menjadi bagian menyedihkan karena sudah dianggap biasa. Mereka hanya memagari sampah-sampah agar tidak bergerak menuju lautan lepas. Namun, seberapa kuat pagar tersebut? Seberapa lama mereka mampu menghadang jika dari hulu terus dilakukan pembuangan sisa-sisa benda atau barang yang sudah tak guna?
“Bagaimana tangkapan hari ini?”
“Lumayan, dua keranjang ini menunggu penawar tertinggi.”
“Sudah laku?”
“Sudah. Tinggal diambil saja.”
Parino, lelaki yang baru dikenalnya itu memiliki perawakan sedang, kulit gelap, mata tajam, dan dada telanjangnya itu bidang. Dua keranjang itu diangkatnya satu per satu menuju pick up yang baru saja tiba. Uang dari sopir pick up itu ia terima. Terlihat ia gemuyu. Dari jauh, didengarnya celotehan Parmin dan Bagio.
“Ngopi, ngopii…” teriak Parmin. Bagio Menimpali.
“Cair, cairr.”
Ia menoleh dua kawannya itu.
“Ayoo,” tawarnya.
***
Aku datang dari tempat yang jauh. Kampung tepi pesisir utara ini menawarkan pemandangan yang tak jauh beda dengan di kampungku. Gadukan ikan, tempat transaksi jual-beli hasil tangkapan ikan, setiap pagi selalu ramai. Para pengepul atau bakul ikan, berlomba mendapatkan kulakan ikan segar dengan harga grosir. Mereka akan menjualnya kembali ke pasar induk.
Beda gadukan sini dengan lelang ikan di tempatku hanya di jenis ikan. Di kampungku, ikan laut yang dihasilkan sedangkan di gadukan ini yang terlihat hanya bandeng. Sesekali, katanya, ada mujair, udang kali, atau wader. Wader menjadi favorit, karena jarang ada. Kalaupun ada harganya relatif mahal.
Parino, lelaki yang baru kukenal itu memiliki perawakan sedang, kulit gelap, mata tajam, dan dada telanjangnya itu bidang. Hasil pengamatan singkatku sudah menemui simpulan bahwa Parino, lelaki yang rajin bekerja. Sewaktu ia sarapan, kulihat makannya cepat sekali. Biasanya orang yang makannya cepat, melakukan aktivitas apapun cepat dan cekatan.
Segelas kopi diteguknya. Nikmat sekali tampaknya. Kopi tubruk kasar, yang ampasnya membumbung hingga permukaan cangkir membuat yang melihatnya sedikit khawatir. Harus hati-hati ia membawanya agar butiran kopi itu tidak meluber keluar dari cangkir. Parino seolah tak peduli, diteguknya sekali lagi dan dikunyahnya butiran kasar bubuk kopi yang memenuhi mulutnya. Sesekali obrolan bersama Parmin dan Bagio ditanggapinya dengan gemuyu.
***
Supinah sampai di kampung ini dan menyaksikan berbagai peristiwa, suasana, dengus napas, suara, pilihan kata, tempat yang pernah diceritakan oleh leluhurnya. Ia tidak sedang datang pada tempat leluhur tetapi ia datang pada tempat yang mengingatkannya pada semua masa lalu. Ia menduga ada kekuatan yang telah menyeretnya menuju tempat ini.
Tentang Parino, ia bertemu secara tak sengaja di warung, dekat gulakan ikan. Lelaki laut adalah julukan yang diberikan Supinah karena secara fisik, Parino memenuhi semua kriteria yang membuatnya berhak mendapat sebutan itu. Lelaki bernama Parino itu terlihat cekatan menimbang tangkapan bandeng hari ini. 30 ribu sekilo, harga yang lumayan menenangkan. Dua keranjang isi bandeng besar menunggu diambil pelelang. Ia terlihat tekun menunggu dan Supinah sangat ingin mengganggunya.
“Bandeng kecil di keranjang sebelah sana sudah tidak segar yaa?” Supinah mulai pembicaraan.
“Iya, agak terlambat. Semoga masih ada yang mau membeli meski pasti harganya jauh lebih murah.”
“Kalau tidak ada yang beli, bagaimana?”
“Nanti dikeringkan saja, jadi ikan asin.” Masih bisa diusahakan supaya tidak terbuang percuma. Nanti di pasar, masih bisa dijual.”
“Berapa lama kamu jadi nelayan?”
“Dari kecil. Ikut bapak.” Wajah Parino menyiratkan kesedihan. Dari mulutnya mengalir cerita masa kecilnya. Bapaknya adalah nelayan sejati dan laut telah memintanya.
“Bapak terseret ombak besar ketika melaut. Mungkin sudah ajalnya untuk bersemayam di lautan. Aku sedih tetapi bangga karena bapak telah membuktikan baktinya pada laut yang sudah setia menghidupi keluarganya.”
Supinah sampai di kampung ini dan menyaksikan berbagai peristiwa, suasana, dengus napas, suara, pilihan kata, tempat yang pernah diceritakan oleh leluhurnya.
“Parino, aku berasal dari tempat yang disebut pada prasasti di depan bale itu. Terus terang saja aku tertarik mengetahuinya lebih jauh.”
Parino menolehku dan menampakkan keseriusan.
“Kakak dari daerah itu? Kakak bisa macapatan? Aku biasanya ikut mempersiapkan acara itu di bale. Nanti sore kita ke sana. Akan kuceritakan lebih lengkap.”
***
Aku mengangguk. Dalam hati, aku sibuk menduga-duga. Prasasti itu telah mencuri rasa penasaran. Delapan kayu penyangga dengan ornamen dan ukiran kayu tanah Blambangan, dikisahkan terombang-ambing di tengah lautan. Kayu penyangga Bale Kambang itu lekuk-lekuknya seperti pernah kulihat, bahkan jari-jemariku pernah menjamahnya.
Mungkinkah benda-benda itu yang mengiringi, memagari, dan mengantarkan keranjang berisi bayi sampai ke sini. Dan karena itulah bayi itu sampai dengan selamat sampai pangkuan Nyai Ageng Pinatih, saudagar wanita kaya itu. Aku semakin bisa menyambungkan rasa ini setelah tahu keseharian warga kampung ini. Lihat saja, logat mereka ketika berbicara, caranya menyeret kata-kata, memberi bunyi-bunyi pelantar, memberi penekanan pada suku kata tertentu. Persis.
Aku Supinah. Kata ibuku darahku biru. Aku tak ingin peduli dengan garis keturunan itu. Tapi entahlah. Ibu selalu memintaku untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak. Katanya lidahku mengandung tuah dan tangan kiriku menyimpan tenaga yang luar biasa. Tentu saja aku sepakat bahwa lisan dan tindak-tanduk kita akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Diterima atau tidaknya kita dalam pergaulan juga tergantung perilaku kita terhadap mereka. Tapi sekali lagi aku tidak ingin berurusan dengan katanya, katanya, meski ibuku sendiri yang mengatakannya.
Namun, yang tak bisa kupungkiri, pikiranku selalu terhubung dengan apa yang terjadi pada kekasihku. Sebelum ia meminangku, pernah ia diberi mimpi yang sama, berturut-turut, selama tiga kali. Mimpi tersebut adalah, ia berada di suatu tempat, semacam gua. Dalam gua tersebut dia menjumpai sebuah pedang yang berkilauan tertimpa sinar di atas batu besar. Ia seperti diminta untuk mengambil pedang itu dan menyimpannya tetapi ia menolak. Malam kedua dan ketiga, ia mendapatkan mimpi yang persis. Untuk kali kedua dia hanya diam mematung tanpa menghiraukan permintaan untuk membawa pedang tersebut. Untuk kali ketiga, akhirnya ia mendatangi pedang berkilauan dengan ukiran yang indah di gagangnya. Diraihnya gagang pedang itu, diletakkan sejajar dengan wajahnya, dan ia menundukkan kepala. Lalu diletakkannya kembali benda bercahaya tersebut di tempatnya semula. Ruangan seperti diselimuti cahaya kebiruan.
***
Parino sudah menyiapkan diri di depan bale. Menurut ceritanya, di bale ini setiap tahunnya, untuk memperingati haul mbah buyut kampung, banyak kegiatan yang dilakukan semua warga kampung, termasuk ritual macapatan. Tetua kampung akan memimpin kegiatan. Uba rampenya ia yang menyiapkan. Kalau di dunia persilatan Parino semacam cantrik atau kalau di lingkungan istana, ia adalah abdi dalem. Parino bertugas menyiapkan dupa, kembang tujuh rupa, jajanan pasar, dan mengeluarkan pusaka sebagai perlengkapan doa sebelum macapatan berlangsung,
Senja menjelang, Supinah masih duduk di teras Bale di temani Parino. Tiba-tiba dari kejauhan seorang ibu tergesa mendekati pelataran bale sambil menggendong anak balitanya. Parino menghampiri.
“Par, anakku badannya panas sekali. Ia mengigau terus. Sepertinya…” Suara wanita itu tertahan.
Parino sigap mengajak ibu tersebut masuk ruangan Bale. Ia mengambil air dari kendi, dipejamkan mata dan mulutnya terlihat khusyu membacakan doa.
“Minumkan air ini walau sedikit, lalu balurkan ke badannya juga.” Semoga cepat turun panasnya.”
“Terima kasih, Par.” Ibu itu terlihat lega dan berpamitan pulang.
Aku menggeser pantat saat Parino menyebelahi dudukku di teras.
“Rupanya jadi tabib juga yaa.”
Parino terlihat biasa saja. Tersenyum saja.
“Sebenarnya tidak juga. Aku hanya mendoakan agar ibunya tenang dan bisa lebih sabar menangani anaknya yang sakit. Itu doa biasa dan bisa dilakukan siapa saja. Ketika ibu itu membalurkan air ke tubuh anaknya, energi kesembuhan akan mengalir bersama keyakinan ibu.
Hampir saja aku keceplosan untuk mengatakan bahwa tangan kiriku juga menyimpan tenaga penyembuh yang aku sendiri belum pernah mencobanya. Dulu ketika aku mendatangi tukang pijat karena tanganku keseleo, tukang pijat itu mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa tanganku bisa untuk menyembuhkan sakit panas yang biasanya terjadi pada anak-anak. Sempat aku bertanya bagaimana caranya. Dia menjelaskan, aku bisa menyembuhkan sakit panas anak dengan perantara degan ijo. Aku harus memetik kelapa muda yang sabutnya berwarna merah muda. Jangan sampai buah itu jatuh dan menyentuh tanah. Sambil tetap dipegang, degan ijo itu dibelah untuk diambil airnya. Tangan kiriku yang harus meminumkan air degan ijo tadi. Ah, buat apa juga kukatakan, karena Parino pun bisa melakukannya.
“Kakak tidak ingin melihat-lihat ke dalam?” tawar Parino
Sebenarnya aku belum selesai melamunkan hal-hal yang kujumpai selama menginjakkan kaki ke kampung ini. Aku masih sibuk dengan pikiranku sendiri. Bahkan ada momen yang membuatku takjub, mengapa sepersis itu. Ajakan Parino tak layak kudiamkan berlama-lama. Segera aku mengikutinya dari belakang.
Minimal ada dua ruangan khusus di dalamnya. Ruangan istirahat dan ruang perlengkapan. Ruang perlengkapan itu menarikku untuk tiba-tiba masuk. Kotak panjang itu menyedot tenagaku. Kubuka pelan-pelan kotak itu. Ada motif dan ukiran yang melekat erat pada ingatanku pada gagang pusaka itu. Kusentuhkan tanganku menyusuri tiap lekuknya. Pelan-pelan juga kurasakan hangat yang mengalir melalui tangan ini, entah apa namanya. Beberapa saat, aku semacam tidak peduli, sedang apa atau sedang berada di mana. Aku hanya ingin diam dan menyelaraskan hati dan pikiran. Di belakangku tegak berdiri Parino. Tubuhnya diam menegang, memandangnya dengan tatapan mata tajam.
“Ternyata engkau pemiliknya Kak. Pusaka itu menerimamu dengan penuh hormat.”
“Kamu siapa, Kak?”
Aku Supinah. Kata ibuku darahku biru. Aku tak ingin peduli dengan garis keturunan itu. Tapi entahlah. Aku hanya ingin berpakansi menurutkan kata hati.
Lahir di Banyuwangi, 18 April 1976. Penulis Buku Kumpulan Cerita Kopi dan Karbit (2017), Buku Kumpulan Puisi: Perempuan Pematah Jalanan (2020), Buku Kumpulan Esai: Menandai Musim Pandemi (2021), Buku Kumpulan Artikel Sastra: Dari Karya Selesa hingga Analisis Memori Sastra Kolonial (2022), Buku kumpulan Puisi: HUN (2022), Buku Kumpulan Cerita: Moto Kece Pake Hape (2022).
Gang Sebelah
Yayasan Gang Sebelah didirikan pada Tahun 2017, sebagai bentuk upaya dalam melakukan penelitian, pengarsipan dan pengembangan Kebudayaan.