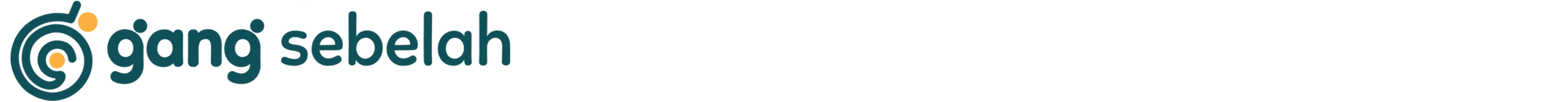Ini semua gara-gara Kang Ojol. Kalau bukan karena mulutnya mengucur deras seperti kran bocor, yakin sekali aku masih bisa merasai hawa Gresik yang khas pantai utara Jawa. Sebentar-sebentar, mataku menerawang sekeliling. Sebentar-sebentar, kembali melihat cermin yang tepat ada di hadapan: tertempel di dinding, di sebelah kiri ujung kaki.
Kulihat jam di layar ponsel, pukul dua malam. Hampir dini hari. Besok padat kegiatan jelas menanti, tapi mataku susah terpejam. Entah timbul dari mana, inisiatif mematikan lampu muncul ketika mataku, yang lebih rajin kugunakan berkedip, tidak timbul rasa kantuk. Ketika lampu padam, dan kegelapan menari-nari di sekeliling, aku justru tidak merasai tenang sama sekali. Meskipun hanya sebentar, berkelebat bayangan-bayangan menyusup pikiran. Apa yang dikata Kang Ojol tadi menjadi sedekat api dengan panasnya. Kunyalakan lagi lampu cepat-cepat, dan kembali baring di kasur.
Beberapa jenak, aku hanya menatap langit-langit. Tidak bergerak, seperti seseorang yang sakit tua. Kupejamkan mata sebentar-sebentar, tapi berkelebat-kelebat perkataan Kang Ojol tadi persis di pelupuk mata. Karena lelah dan tidak lekas tidur, hatiku menjadi dongkol tiba-tiba. Tentu saja kepada Kang Ojol. Tapi, lebih dari itu, aku menyesali keputusanku buat berkunjung ke Makam Maulana Malik Ibrahim dan Makam Jaka Samudra dan pulang menggunakan ojol dan mendengar cerita seram dan mataku susah diajak terpejam.
Lima jam, kalau tidak salah, sebelum peristiwa tidak mengenakkan ini terjadi, kami mendapat pengarahan dari pembimbing KKL (Kuliah Kerja Lapangan). Beliau-beliau itu, menyampaikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau merugikan di tempat ini, kata beliau. Aku sudah tahu itu, dan kupikir tidak hanya aku saja. Sambil terkantuk-kantuk kuusahakan menyimak yang diarahkan oleh pembimbing. Pengarahan selesai, dan kami dipersilakan menuju kamar masing-masing, sambil menitip pesan: kami boleh berkeliling daerah sekitar hotel asal kembali sesuai waktu yang ditentukan.
Aku cukup kaget, kenapa panitia KKL memilih tempat menginap seperti ini: bangunan tua penuh nuansa kolonial. Kata mereka tadi, setelah temanku bertanya, biar kami bisa merasai Gresik sepenuhnya. Kupikir, alih-alih dapat merasai Gresik, yang ada justru nuansa seram yang melekat di dinding hotel. Di kamar, ketika kesepian dan keheningan merebak begitu saja, aku tidak jadi mengantuk.
Kulihat lagi ponsel, untuk mencari tempat-tempat terdekat yang dapat meredakan kesuntukan. Makam Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri muncul paling atas. Cepat saja, aku cangklong tas dan memasang sepatu. Kupikir, makam dapat menghilangkan kesuntukan sekaligus mendatangkan hawa sejuk yang dapat menyangkal kehangatan hawa pesisir. Pihak hotel bersedia mengantarku, satu kali belok kiri, lalu belok kanan tanpa obrolan, melewati alun-alun Gresik, aku sudah sampai di Makam Maulana Malik Ibrahim.
Soal Makam, dulu aku sempat diajak kakekku melakoni ritus ziarah semacam ini. Mendatangi makam leluhur atau orang yang dituakan, lalu berdoa beberapa jenak. Bila di kampung-kampung, makam-makam yang kudatangi kurang terkenal, sehingga hawa ketenangan menempel di sekitar tempat seperti itu. Tapi di sini lain, Maulana Malik Ibrahim seperti tak sempat sepi.
Turun dari motor, langsung dihadapkan pada nuansa ziarah komersial. Sandal tampak kocar-kacir memenuhi pelataran pintu masuk. Kugeletakkan begitu saja sandalku. Beberapa orang tampak kelelahan. Di gapura candi bentar, yang sebenarnya tidak memisahkan kompleks peristirahatan dengan makam, aku meraba-raba motif yang sudah kabur. Di depan sebelah kanan gapura ini, persis tiga makam terbujur, salah satunya adalah Maulana Malik Ibrahim.
Orang-orang bergerombol di depan tiga bujur makam, berwirid, tapi lebih cocok dibilang berteriak. Kepala mereka bergerak serentak ke kiri ke kanan. Aku urung mendapatkan kesejukan, sebab keramaian yang begitu rupa. Masih kurasakan hawa pesisir yang hangat, atau lebih cocok dikatakan panas.
Kucoba membaca surat Yasin, dari kejauhan saja, di salah satu tiang penyangga yang memayungi makam Maulana Malik Ibrahim. Setelah beberapa jenak, tandas kubaca Yasin, kunikmati udara sejuk yang akhirnya menghampiri. Tidak ada lagi orang berteriak-teriak, mereka sudah tergantikan dengan rombongan yang melantunkan wirid lebih hikmat. Kesejukan akhirnya sedikit-sedikit kunikmati.
Aku memandang kosong apa saja yang terhidang di depan mata. Lanskap makam, lalu-lalang manusia, orang yang tergeletak begitu saja karena kelelahan, dan macam-macam. Tentu saja pada akhirnya kembali terlempar ke kamar hotel karena ada bunyi yang cukup membikin pikiran ke mana-mana.
Waktu aku sedang menikmati pikiran yang sedang membayang ke kejadian beberapa waktu tadi. Bunyi orang berjalan menyeret sandal terdengar di luar kamar. Mataku langsung membelalak ke mana-mana, menatap apapun, dan terpaku pada cermin yang menampakkan polos tembok. Bulu kudukku merinding setajam duri landak. Mataku melirik ke kiri dan kanan, kalau-kalau ada sesuatu di sana. Kengerian seperti menjadi-jadi, apakah teman samping kamarku mendengar hal serupa? Aku kembali merutuki Kang Ojol tadi. Dan tentu saja ketololanku, kenapa pulang dari makam memesan ojek online.
Jadi, waktu pihak hotel mengantarku ke makam, dia bilang kalau sebenarnya hotel dengan makam lumayan terjangkau dengan jalan kaki. Dan itu benar, hanya perlu dua belokan dari hotel sudah sampai. Sesampai di makam pun, aku membayangkan betapa kembali ke hotel nanti cukup enak jika jalan kaki sambil menikmati lanskap alun-alun dan pesona kota tua Gresik dan berjejer-jejer penjaja kopi. Tapi, itu semua urung terjadi sebab kejadian di Makam Maulana Malik Ibrahim.
Sehabis membaca Yasin, kantuk melahapku begitu saja. Kantuk yang tertunda sejak dari hotel tadi. Pada akhirnya hawa pesisir tak lagi kurasakan. Aku seperti sedang ditiupkan doa tidur oleh Maulana Malik Ibrahim. Sambil bersandar seperti posisi semula, aku tertidur, dan ternyata lumayan lama. Aku dibangunkan oleh suara keras, kurasa itu kalimat tahlil tapi menjadi kabur karena dilantunkan terlalu cepat dan tidak teratur.
Sebelum itu, kurasai sesosok bercahaya dengan jubah putih muncul tepat di pelupuk mata. Aku tersentak, seturut dengar pekikan kalimat tahlil yang tak teratur. Pandanganku menggapai sekeliling. Lalu berhenti di layar ponsel. Kulihat jam telah menunjukkan pukul dua belas lebih sedikit.
Agak tergesa-gesa akhirnya, kuputuskan buat menuju Makam Sunan Giri. Aku berkejaran dengan waktu. Kupesan ojek online yang ternyata masih tersedia di waktu sebegitu malam. Ojek online meluncur ke titik jemput, sementara kakiku bingung mencari sandal yang tadi kugeletakkan begitu saja. Bertepatan dengan ojol sampai di lokasi jemput, sandalku yang berpisah di sebelah kiri dan kanan pintu masuk kutemukan.
“Asli sini, Mas,” kata Kang Ojol sewaktu motor baru melaju.
“Bukan, Pak,” kataku, “Saya asli Malang.”
Kang Ojol manggut-manggut, helmnya bergerak terantuk-antuk. Ia cukup aktif mengajakku ngobrol, mulai soal plat motor, industri, UMK, dan macam-macam, hingga sampailah pada pertanyaan.
“Tinggal di mana, Mas?” Kang Ojol
“Di Hotel Bagi-Aha, Pak,” Kang Ojol langsung diam. Dia tak lagi mengajakku ngobrol, bahkan sampai di depan parkir Makam Sunan Giri. Ketika aku turun dari motor, ia hanya menyisipkan kata, “Hati-hati, Mas.”
Kupikir, respon yang diberikan Kang Ojol setelah mendengar tempat di mana aku menginap cukup aneh. Bila sebelumnya ia menanyai macam-macam, setelah mendengar nama Hotel Bagi Aha, tempatku menginap, bibirnya langsung mengatup.
Orang-orang ojek pengkolan banyak menawariku buat mengantar ke Makam Sunan Giri tanpa perlu meniti tangga tinggi menjulang. Dengan tatapan mata, aku menolak sopan. Menaiki tangga semacam ini, kupikir, memiliki sensasi tersendiri. Untuk menuju puncak, mencapai tujuan, kita perlu bersusah-susah terlebih dahulu. Ya, kalau secara filosofis seperti itu, tapi kupikir meniti tangga menuju makam termasuk salah satu hal esensial dalam ziarah yang wajib ditunaikan, dan tentu saja supaya bisa menikmati suasana makam sambil berbasah-basah keringat.
Setelah melewati tangga, mataku disuguhkan dengan pemandangan ziarah komersial yang tidak jauh beda dari Makam Maulana Malik Ibrahim. Bedanya, Makam Sunan Giri terletak di cungkup utama, yang hanya cukup dimasuki oleh belasan orang. Kucoba masuki cungkup utama. Meskipun cukup sempit, hawa panas di sana tidak terasa membakar. Kami, yang berada di cungkup utama, dibatasi hanya lima belas menit untuk mengirim doa. Selesai melakoni ritus itu, aku memilih pulang, takut kalau-kalau dimarahi oleh panitia KKL sebab melewati batas waktu yang ditentukan.
Di pelataran parkir, tentu saja setelah menuruni tangga curam dengan panorama kiri-kanan gelap gulita, kupesan ojek online. Berharap-harap, semoga masih tersedia dan tentu saja dengan tarif yang lebih murah dari ojek pengkolan. Harapanku makbul, setelah beberapa jenak, Kang Ojol yang bakal menjemputku bilang melalui pesan; “Jangan di area parkir, Mas.” Aku mengiyakan dan segera membalas, “Kalau bapak sudah sampai, nanti kasih tahu di mana tempat bapak.”
Waktu menanti Kang Ojol dengan aku menjajal pentol Makam Sunan Giri. Tak lama, layar ponselku menampilkan pesan dari Kang Ojol, “Mas, saya di depan mobil biru agak ke utara dari parkiran!”
Aku ke sana, meski sedikit dongkol sebab mobil biru yang dimaksud cukup jauh dari parkiran. Tapi, pada akhirnya, Kang Ojol menjelaskan kenapa ia memintaku buat sedikit jauh dari parkiran. Katanya, sering terjadi konflik antara Ojol dan Opang soal jatah penumpang. Openg merasa dirugikan jika pengunjung ziarah lebih memilih Ojol, sementara mereka sudah menawarkan sedemikian rupa untuk mengantar-jemput pengunjung. Aku menyimak terkantuk-kantuk, sampai Kang Ojol itu menanyai dengan terheran-heran kenapa aku memilih Hotel Bagi-Aha sebagai tempat menginap.
“Itu yang menyediakan panitia, Mas,” kataku. “Dan tempatnya cukup enak, nuansa lama lumayan terasa. Kenapa memangnya, Mas?”
Kang Ojol tidak menjawab. Mungkin kurang dengar, sebab kali ini ia memacu motornya sedikit kencang. Lalu, ia bertanya lagi, soal sudah tahu, kan, Hotel Bagi Aha itu seperti apa?
Kujawab lagi dengan sedikit mengulang, “Sudah, Mas. Tempatnya cukup nyaman, kok.”
“Tempatnya gimana, Mas?”
Aku menangkap keanehan. Pasti ini ada apa-apa soal tempatku menginap. Pertanyaan itu kujawab dengan sedikit mengulang pula, “Cukup terawat, Mas, dan di sana lumayan nyaman.”
Kang Ojol manggut-manggut, helmnya terkantuk ke depan-belakang. Lalu tidak ada percakapan lagi. Setelah melewati beberapa kali belokan, dan Hotel Bagi Aha tertangkap mata, Kang Ojol bilang dengan entengnya, “Mas, di Hotel Bagi Aha itu pernah terjadi pembunuhan. Makanya sempat ditutup permanen. Tapi, nggak tahu kenapa ini bisa dibuka lagi.”
Mendengar kata pembunuhan yang meluncur begitu saja, tulang-tulangku seperti dibredel dari daging yang mengikatnya. Jantungku mencelos. Aku tak bisa membayangkan, bila beberapa hari berikutnya aku harus tidur, harus melakukan aktivitas di tempat yang pernah terjadi pembunuhan. Untuk menenangkan hati sekaligus berusaha berpikir positif, kutanyakan lagi maksud pembunuhan kepada Kang Ojol, apakah pembunuhan itu adalah pembantaian di era kolonial dulu, sebab tempatnya, kan, memang ada sejak zaman kolonial.
Tapi, kata Kang Ojol itu yang akhirnya malah membikin merinding. Pembunuhan di Hotel Bagi-Aha baru terjadi tahun 2000-an ini. Meskipun, Kang Ojol bilang tidak tahu persis dua ribu berapa, tapi jarak kejadian itu kuterka-terka masih cukup dekat dengan 2023.
Sesampai di Hotel aku seperti enggan turun dari motor Kang Ojol. Pantatku seperti lengket di jok motor. Tapi, bagaimanapun kupaksa menjinakkan ketakutanku ini. Turun dari motor dengan mengucap ‘terima kasih’ di lobi hotel, aku disambut oleh petugas yang tersenyum ramah. Aku terpaku sebentar. Seperti tiang garam.
Kutelusuri layar ponsel tentang hotel tempatku menginap. Berharap-harap kalau Kang Ojol tadi salah informasi. Sayangnya, secepat kilat, pencarianku menunjukkan kalau di Hotel Bagi-Aha memang pernah terjadi pembunuhan, tercatat tahun 2004, entah atas motif apa, cepat-cepat kututup ponsel dan berlari menuju kamar tidur. Dan, seperti inilah akhirnya. Di kamar tidur aku tak bisa tidur.
Beberapa kali, mataku memandang cermin di hadapan. Kupingku kerap mendengar bunyi-bunyian aneh. Sandal diseret, benda-benda jatuh. Pikiranku terus melayang, menebak di kamar sebelah mana pembunuhan itu terjadi.
Kalau aku tidak sok-sokan kepingin mengunjungi Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri, tentu saja tak bakal kutemui mulut bocor Kang Ojol, dan tentu saja pula, aku tak bakal mendengar berita yang membikin mataku tak berani terpejam dan pikiranku melayang-layang. Aku meratapi ketololan itu sambil mencari kembali hawa pesisir yang terganti dengan keringat dingin.
Malang, 25 November 2023
M. Isnaini Wijaya, lahir di Kediri, 22 Juli 2003. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Besar keinginannya untuk dapat membaca seratus buku setiap tahun. Dapat ditemui di ig: ikiisna_
Residensi Literatutur mengundang 18 Penulis di Indonesia untuk diundang ke Gresik dalam upaya melakukan pembacaan, penggalian ide, dan menemukan gagasan atau kemungkinan lain yang kemudian dituangkan dalam cerita pendek. Residensi ini diadakan oleh Yayasan Gang Sebelah yang didukung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Gang Sebelah
Yayasan Gang Sebelah didirikan pada Tahun 2017, sebagai bentuk upaya dalam melakukan penelitian, pengarsipan dan pengembangan Kebudayaan.