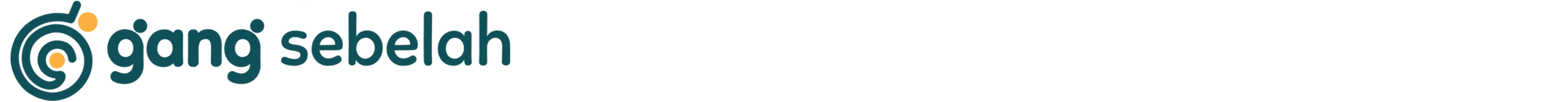Tatapannya hampa. Jemarinya beku. Canting yang dia pegang dibiarkannya mengambang di udara. Tak ada goresan cairan malam yang memenuhi kain mori seperti biasanya. Hingga lilin itu pun dingin, segigil udara yang menyelimuti hatinya kini.
Ini sudah bulan ketiga sejak permintaan yang dirasa mustahil itu. Biasanya Wening bisa menyelesaikan batik tulis dalam waktu tiga bulan. Saat Wening benar-benar menikmati prosesnya, dia bahkan bisa menamatkannya hanya dalam waktu sebulan. Sepanjang hari Wening hanya akan berkutat di depan tungku, berkawan wajan dan canting. Jemarinya sibuk menari-nari di atas kain mori.
Namun kini, retina Wening hanya menyisir motif-motif kain batik yang tergantung di gawangan. Pandangannya lantas tertumbuk pada sebuah kain berwarna biru dengan motif perahu. Wening memperhatikan garis-garis bergelombang dengan dua buah ikan yang melompat. Ingatannya melayang pada saat dia menikmati aroma laut di kawasan pesisir bersama lelaki itu. Dicelupkan kedua kakinya ke dalam air. Wening duduk santai di papan kayu. Kedua lengannya terbentang. Matanya menerawang jauh ke arah lautan tak bertepi. Angin sepoi-sepoi membelai wajahnya lembut.
“Aku jadi kepikiran untuk bikin motif perahu,” ujar Wening setelah menikmati dua puluh detik yang hening.
“Perahu dan laut, perpaduan yang menenangkan.” Yudistira ikut duduk di samping Wening.
“Biar aku bisa mengabadikannya, tempat favorit kita.” Wening melempar senyum.
“Kau selalu punya ide saat kita jalan-jalan.”
“Inspirasi itu hadir saat hati sedang bahagia.”
“Hmm, begitu, ya. Apa kau akan terus membatik selamanya?”
Wening mengangguk mantap. “Batik itu sudah seperti napasku.”
“Bagaimana kalau keadaan memaksamu untuk tidak membatik?”
Wening mengedikkan bahu. “Entahlah, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa oksigen.”
Kini, pertanyaan Yudistira itu seolah menjelma nyata. Wening tak lagi mengisi hari-harinya dengan membatik. Hatinya menjelma rumah tak berpenghuni, muram dan suwung, seolah ada yang dipaksa tercerabut dari sana. Namun, memaksakan diri untuk menorehkan cairan lilin sama halnya dengan mengoyak luka lama yang belum kering. Wening seperti berdiri di atas dua perahu.
***
Di suatu senja yang paling merah, Wiraguna dan Suryanegara tengah duduk di teras rumah Surya yang luas. Di antara mereka terhidang dua cangkir kopi yang masih mengepulkan uap panas. Surya menyesap khidmat lintingan tembakau di tangannya sebelum mulai bersuara.
“Menikmati hari tua tanpa melakukan apa-apa sama halnya dengan menunggu Izrail menjemput.” Surya mendesah panjang. Asap melesat dari lubang hidung dan mulutnya. “Bagaimana kalau kita bikin usaha bersama?”
“Bisnis itu perlu modal besar, Mas.”
“Kau tenang saja, uang pensiunku cukup untuk membuat bisnis kecil-kecilan. Untuk permulaan, kita tak perlu sewa tempat. Ruang tamuku akan kusulap jadi tempat usaha,” papar Surya penuh ambisi.
“Memangnya kamu mau bisnis apa?” Wira mencondongkan tubuhnya menghadap ke arah Surya.
“Kau kan jago membuat pola batik. Aku ingin bikin usaha batik.”
Tawaran Surya terdengar menggiurkan bagi Wira. Dari dulu, dia memang tak ingin bekerja yang menguras pikiran. Wira hanya ingin bersenang-senang, menikmati setiap pekerjaannya. Dan membuat pola batik bagi Wira tak ubahnya bermain layangan.
Perjalanan membuka usaha batik itu pun dimulai keesokan harinya. Surya memanggil beberapa orang tukang untuk merenovasi teras dan ruang tamunya. Beberapa etalase, gawangan, dan perlengkapan untuk membatik didatangkan dengan mobil pick up pada sore hari. Sementara Wira mulai sibuk menggali ide motif yang akan dibuatnya. Tiga cangkir kopi menemaninya hingga malam semakin meninggi. Meski tubuhnya berlumur lelah, otaknya tak bisa berhenti menuangkan ide-ide untuk membuat motif batik.
Awalnya, usaha batik kakak beradik itu berjalan mulus. Keuntungan usaha dibagi dengan adil setelah dikurangi biaya operasional. Wira sanggup memenuhi pesanan batik yang masih hitungan jari. Namun, begitu pesanan membludak, Surya mulai merekrut beberapa orang karyawan baru untuk membantu menyelesaikan pesanan. Hingga suatu ketika, Surya memecat Wira secara halus.
“Apa kau tidak ingin membuat usahamu sendiri?” tanya Surya basa-basi.
“Bukankah rumah batik ini usahaku juga, usaha kita?” Wira balik bertanya, tak mengerti. “Maksudku, kau kan jago membuat pola batik. Akan lebih baik kalau kau bisa mengembangkan merk batikmu sendiri. Keuntungan hasil usaha milikmu pasti cukup untuk dijadikan modal.”
Wira diam seribu bahasa. Menurutnya, membuka usaha baru tidak semudah membalik telapak tangan. Terlebih jika usaha bersama mereka sudah berjalan sekian lama sementara dia harus memulai lagi dari nol. Mereka sudah punya lumayan banyak pelanggan. Lagi pula Wira tak ingin menyaingi usaha kakaknya.
“Kau tenang saja, aku sama sekali tak merasa tersaingi,” ucap Surya seolah bisa membaca isi kepala Wira. “Aku justru senang kalau kau bisa mengembangkan usahamu sendiri.”
Wira menghela napas panjang. Baiklah kalau itu yang Surya inginkan. Bukankah usaha batik ini juga idenya? Kalau sekarang kakaknya itu ingin usaha sendiri, itu haknya.
***
Satu pekan setelah pembicaraan terakhir mereka, Wira mendengar kabar kalau Surya sudah mematenkan merk batiknya sendiri, batik Negara. Dan yang menjadi primadona batiknya itu adalah motif keris. Keris yang melambangkan kekuatan dan kesaktian. Keris? Kening Wira memberengut. Seketika dia mengumpat dalam hati. Bukankah motif itu adalah gagasannya? Wira pernah bercerita pada Surya kalau dia ingin membuat motif keris dengan ornamen aksara jawa. Unik saja menurutnya.
Dan sekarang Surya menggunakan motif itu dan mengklaim motif keris sebagai produk batik Negara. Hmm, pantas saja Surya memecatnya secara halus dengan dalih memintanya membuka usaha sendiri. Kakaknya itu lebih memilih membayar orang untuk membuat pola batik dibandingkan harus berbagi laba dengannya. Mungkin keuntungannya jauh lebih besar.
Nama batik Negara menjadi lebih dikenal setelah Pak Bupati mengenakannya dalam acara resmi Kabupaten. Media lokal yang meliput berita tersebut membuat merek batik Surya semakin melambung. Surya pun serasa di awang-awang sementara Wira jatuh berdebum. Jauh di dalam lubuk hati Wira, api kemarahan telah berpendar. Dia ingin membuktikan kalau usahanya bisa jauh lebih berjaya dibandingkan usaha sang kakak. Dendam positif. Dendam yang menjadi meledakkan semangatnya untuk berkarya lebih.
Maka, dimulailah hari-hari Wira untuk menghidupkan usaha batiknya. Dia ingin fokus menghasilkan batik tulis yang berkualitas. Dengan bantuan Wening, anak semata wayangnya, Wira bisa menghasilkan batik-batik dengan motif yang apik dan unik. Apalagi proses pemasarannya tidak hanya melalui etalase rumahnya, tapi juga lewat media sosial dan toko online.
Motif batik buatan Wening terbukti lebih laris di pasaran dan lebih disukai pembeli dibandingkan motif batik buatannya. Entah, mungkin Wira sudah terlalu tua untuk membatik. Atau mungkin dia sudah tak lagi menikmati kesenangan membatik karena tujuannya membatik hanya untuk balas dendam. Akan tetapi, sejak kejadian itu, Wening layaknya manekin tanpa jiwa. Dia juga kehilangan rasa untuk menorehkan sebuah karya.
***
Siang itu, Wiraguna menghampiri Wening dengan wajah semringah. Langkahnya sedikit terburu-buru. Tampaknya dia sudah tak sabar untuk menyampaikan sebuah berita penting.
“Nduk, ada pesanan,” ungkapnya.
Wening tak mengalihkan pandangannya dari buku yang tengah ditekurinya.
“Dari Pak Gubernur,” tambah Wira dengan antusias.
Namun, Wening tetap bergeming.
“Nduk ….” Wira memegang kedua bahu Wening. Mau tak mau Wening menatap mata bapaknya.
“Biasanya Bapak membuat desain motifnya sendiri dan meminta tolong orang untuk membatiknya, tapi kali ini berbeda, Nduk.” Sorot mata Wira mengisyaratkan permohonan yang sangat. “Bapak harap kamu yang akan menyelesaikannya kali ini.”
Ada jeda yang terasa panjang menyelimuti keduanya.
“Wening nggak bisa, Pak.” Sejak pertikaian Wira dan Surya, Wening serupa penulis yang kehilangan kata-kata.
“Kamu pasti bisa, Nduk.” Wira mencengkeram bahu Wening lebih kuat, seolah hendak menyalurkan kekuatan.
Wening menggeleng lemah. Kepalanya layu.
“Pak gubernur memberi waktu yang cukup panjang. Rencananya, batik ini akan dipakainya untuk acara resmi provinsi. Kalau kamu bisa menyelesaikannya dengan baik, merk batik kita bisa terangkat media dan penjualan bisa jadi meningkat.”
Wening memutar bola matanya, tak tertarik.
Wira mengambil kedua tangan Wening dan menggenggamnya erat. “Bapak mohon, Nduk. Bantu Bapak kali ini saja. Setelah itu, Bapak janji, Bapak nggak akan minta kamu untuk membatik lagi.”
***
Jemari Wening menyusuri motif walet berwarna biru tua. Di sekeliling walet itu dihiasi lengkungan-lengkungan serupa daun yang menjari. Dia terinspirasi membuat motif walet setelah menyusuri kampung lawas. Dulu, hampir semua rumah di daerah tersebut dijadikan tempat untuk beternak walet.
Netra Wening kembali merayapi motif-motif kain batik yang tergantung di gawangan, seolah tengah mengabsennya satu per satu. Desain motif pada kain batik itu mempunyai sejarahnya masing-masing. Wening baru ngeh kalau ide membuat desain itu didapatnya saat berjalan-jalan bersama Yudistira.
Yudistira memang suka sekali jalan-jalan. Begitu pun dengannya. Entah itu hanya sekadar menikmati malam di alun-alun atau menyusuri kawasan kota lama. Menikmati kuliner lokal dan mengobrol panjang lebar dengan penduduk sekitar. Cerita-cerita itu menyalakan lampu di kepala Wening. Namun pada akhirnya, kenangan bersama Yudistira harus lebur bersama lilin yang mencair.
Setelah Surya mematenkan motif batik karya Wira, bapak Wening melarangnya berhubungan dengan Yudistira. Sebabnya tak lain karena Yudistira adalah anak Surya. Saat mencium aroma permusuhan yang kental—yang sebenarnya diciptakannya sendiri—Surya pun ikut-ikutan tak memberi restu pada hubungan Yudistira dan Wening. Pergerakan keduanya selalu dibatasi dan diawasi layaknya tahanan rumah.
Sudah berkali-kali Yudistira berusaha mencuri kesempatan untuk mengajak Wening keluar, tapi selalu ketahuan. Hingga puncaknya, Yudistira menitipkan sebuah surat pada Wening melalui kawan baik gadis itu. Yudistira berpura-pura keluar rumah sendirian di siang hari. Agar tidak ketahuan, Wening dan kawannya baru berangkat sore harinya. Mereka pun menuangkan rindu di sepanjang jalan menuju kawasan pelabuhan lama, tempat favorit keduanya untuk melihat laut. Namun naas, dalam perjalanan pulang, Yudistira yang mengendarai motornya sendirian mengalami kecelakaan.
Lompatan kenangan itu tiba-tiba menyengat sel-sel syaraf di otak Wening. Gadis itu bergegas mencari kunci motor. Dia lantas melajukan motornya menyusuri kawasan kota lama. Memasuki gang demi gang, melewati kampung Arab dan kampung Pecinan. Dia hanya ingin memutar ulang kenangannya bersama Yudistira. Saat melewati rumah-rumah berarsitektur unik, di benak Wening berlompatan ide untuk motif batik. Bagi Wening, Yudistira adalah rumah. Namun, Wening masih tak yakin bisa menuangkannya ke dalam kain mori. Sebab, kain putih itu telah membawa cintanya pergi. []
Mega Anindyawati, lulusan Sastra Inggris Universitas Airlangga yang berdomisili di Sidoarjo. Saat ini tergabung sebagai tim divisi karya Forum Lingkar Pena (FLP) Jawa Timur. Ia beberapa kali menjuarai lomba menulis dan menjadi narasumber kelas menulis. Tulisan-tulisannya pernah dimuat di Jawa Pos, Kompas, Radar Mojokerto, Harian Bhirawa, dan beberapa media lainnya.
Gang Sebelah
Yayasan Gang Sebelah didirikan pada Tahun 2017, sebagai bentuk upaya dalam melakukan penelitian, pengarsipan dan pengembangan Kebudayaan.