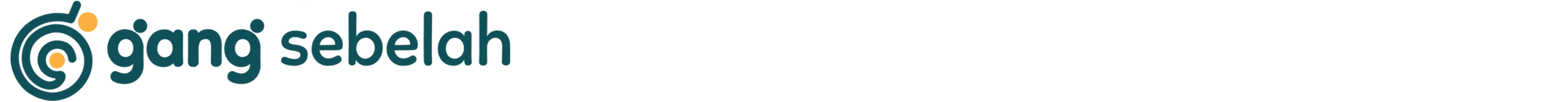Menyendiri ada kalanya jadi jamu paling mujarab bagi jiwa dengan luka menganga. Meski mengurung diri di kamar pada malam bulan Ramadhan ini seperti menelan pil pahit saat sakit. Inginku bermuhasabah di langgar belakang rumah agar khusyuk merapal ayat-ayat suci-Nya bersama warga Desa Lumpur. Tapi itu mustahil.
Pikiranku sudah terlampau riuh. Gemuruh oleh bayang-bayang cacian sambung-menyambung Cak Muhaimin dan Cak Mudzil sore itu. Masih membekas. Bagaimana mungkin mereka tega menunjuk batang hidungku tepat di depan jamaah lain?
Kemarin di halaman langgar, suara parau kedua cacakku bisa didengar oleh para jamaah Langgar. Kedua cacakku kompak menudingku durhaka. Hinaan mereka sukses memberiku cap manusia paling berdosa karena gagal mengembangkan bisnis warisan walet milik bapak.
“Anak durhaka. Bisa-bisanya kamu mau mengubah jadi kos-kosan!”
Belum selesai Cak Muhaimin menyambar dengan ucapannya, Cak Mudzil menimpali, “Kami sudah berikan warisan itu ke kamu bukan berarti kamu bisa seenaknya mengganti hanya demi uang! Jangan gampang putus asa gitu, lah! Kamu tahu kita ini sudah generasi kelima. Masak mandeg di kamu?”
Sudah coba kutepis ucapan mereka kemarin sore. Tapi otakku terlanjur merekamnya. Bak radio rusak, otakku memutar kembali lengkap dengan gambaran suasananya. Kalau sudah begini, rasanya ingin kucuci otakku pada bagian itu agar tak memikirkan lagi.
Ambyar sudah niat beriktikaf di langgar malam ini. Aku tak bisa membayangkan Cak Mudzil melanjutkan hinaannya. Diikuti Cak Muhaimin yang menghujaniku ceramah bisnis berjam-jam lamanya seolah aku belum pernah mencoba.
Mereka lupa bagaimana malam itu, setelah bapak meninggal, tak ada yang mau mencoba meneruskan bisnis sarang burung walet peninggalan bapak. Aku masih ingat waktu Cak Mudzil dengan bekal gelar Sarjana Kimia-nya bersikukuh menjadi pegawai pabrik terbesar di Gresik kala itu.
Meski penghasilannya kalah dari bisnis sarang burung ini, Kakak sulungku membangun rumah sendiri di pusat kota Gresik. Rumah yang dibangunnya hanya berjarak 30 menit dari rumah peninggalan bapak. Semenjak itu, ia ogah-ogahan mengurus rumah warisan sarang burung walet peninggalan bapak, tak lama ia serahkan urusan rumah walet ini padaku.
Begitu pula Cak Muhaimin. Setelah beberapa tahun menyandang gelar dokter, dia mau fokus melanjutkan studi spesialisnya. Di masa hidupnya, Almarhum bapak tidak pernah setuju Cak Muhaimin menjadi dokter, apalagi mengambil program pendidikan spesialis penyakit dalam. Bapak takut dia tertular penyakit aneh-aneh meski sudah berulang kali Cak Muhaimin menjelaskan kemuliaan profesinya.
Kepergian bapak menjadi angin segar. Tidak ada lagi gembok penghalang melanjutkan pendidikan spesialis itu. Rumah warisan di sisi selatan rumah yang aku tinggali ini, dengan sarang burung waletnya di lantai dua, juga dia berikan padaku.
Mungkin karena waktu itu aku masih baru lulus Sarjana Ekonomi. Latar belakangku dinilai paling cocok untuk mengelola sarang burung warisan bapak. Lagian tak ada pilihan lain bagi anak bontot yang masih mencari kerja setelah lulus Sarjana. Dengan ragu aku meneruskan mengelola tiga rumah bersarang burung ini.
Di rumah warisan yang aku tinggali juga ada sarang walet di lantai dua. Rumah kami berjajar. Bentuknya sama, warna dinding dan perabot di dalamnya saja yang berbeda. Bapak sepertinya sengaja mendirikan rumah kembar tiga untuk keadilan, memberikan investasi masa depan bagi ketiga anaknya.
Tapi bapak tidak sadar kalau dua anaknya sudah jadi orang, tak perlu warisan sarang burung untuk merajut hidup layak di pesisir kota Gresik. Hanya satu anaknya yang masih butuh bantuan: seperti cahaya damar yang redup.
**
Samar-samar terdengar seseorang mengetuk pintu. Kepalaku agak pusing. Berat sekali membuka kelopak mata. Mungkin karena terlalu lama menangis semalam. Kamar ini membuatku aman melepas air mata tanpa dilihat orang, termasuk istriku.
Aku mengurut kepalaku yang pusing, meski rasanya tak berkurang. Bisa jadi terlalu lama otakku memutar ulang adegan memalukan adu mulut dengan kedua cacakku. Atau karena aku memang terlalu lemah, tidak berdaya, mudah menyerah dan bodoh seperti kata mereka.
Pintu kamar diketuk keras-keras. Ketukan itu semakin keras bersamaan dengan memanggil namaku. Tidak salah, Sundari. Suara khasnya aku rindukan, memaksaku membuka mata sehingga tampak cahaya surya dari balik gorden yang menari seiring embusan angin pagi.
“Mas Damar, eson ngerti lho sampeyan wis tangi. Wis tak masakno lontong rumo senengane sampeyan. Kerupuke wis tak pisah, sambele rong sendok kayak biasae. Kangkung, daun singkong seger, Mas. Ayo, sarapan bareng!” Aku masih menggeliat di amben kapuk. Rasanya tidak berdaya untuk sekadar menjawab istriku yang kelewat sabar.
Sundari tentu hafal dengan kebiasaanku mengurung diri. Di kamar bapak ini tempat aku mencari ketenangan. Beruntung, Sundari memberiku ruang berlindung dari penghakiman manusia di luar sana yang seenaknya.
“Mas, masih butuh waktu sendiri? Lontong rumonya di meja. Kalau Mas pengen embo, masih ada di panci.” Sesaat kemudian terdengar piring berderit saat Sundari meletakkannya di meja marmer. Meja itu peninggalan bapak. Aku mengelapnya setiap hari, kecuali saat mengurung diri begini.
Dari derap langkah yang terdengar, Sundari semakin menjauh. Entah ke mana. Aku masih bergeming. Tapi kali ini sudah duduk di tepi amben lalu berjalan mendekati pintu kamar. Kutempelkan telingaku di daun pintu untuk memastikan tidak ada seorang pun di dekat kamar. Kubuka pintu perlahan. Di atas meja dekat pintu sudah ada piring dengan sepincuk lontong rumo dan secangkir kopi kasar kopyok. Buru-buru kubawa masuk lalu kututup lagi pintu kamar ini.
Rasa lontong rumo buatan Sundari memang enak. Dalam sekejap sudah habis, tinggal beberapa remah kerupuk, bisa kumakan dengan bubur berwarna oranye yang gurih pedas. Dia pasti mencampurkan banyak udang segar.
Menu sarapan ini kembali membawa ingatanku pada bapak karena ini juga menu sarapan kesukaannya. Di detik-detik terakhir dia bernapas, bapak mendoakanku menjadi orang, sukses seperti Cak Muhaimin dan Cak Mudzil. Bapak tidak mengharuskan aku mengelola sarang burung ini. Hanya bapak akan sangat senang kalau ada dari anaknya yang bersedia melanjutkan warisan ini.
“Temukan cahayamu sendiri, Nak. Bapak yakin kelak kamu akan bersinar terang,” demikian pesan terakhir bapak. Tangan keriputnya menggenggam tanganku lalu mengucapkan istirja. Air mataku kembali mengalir. Dadaku sesak mengingat pesan bapak. Mungkin Cak Mudzil benar. Aku telah menjadi durhaka karena menyerah dengan kondisi bisnis yang omsetnya terus menurun.
Sambil menyesap kopi yang sudah kuangkat ampas kasarnya empat menit yang lalu, aku membuka lagi lembar-lembar daftar pengembangan bisnis ini. Semua usaha sudah aku lakukan. Bahkan sampai kuputarkan rekaman suara sriti dan walet yang kata orang ampuh mengundang walet.
Ingin aku demo pada pabrik di dekat pelabuhan itu. Pasti polusinya membuat walet-walet ini mengungsi ke daerah lain. Tapi itu artinya aku juga berdemo pada industri tempat Cak Mudzil meraup upah yang sangat ia banggakan.
Aku menyesap kopi sekali lagi sambil menerawang langit yang cerah. Kali ini pahit dan asamnya mengingatkanku pada omongan tetangga kapan hari. Kata istriku, Bu Sabar dan Bu Rahman yang tinggal di samping utara mengeluhkan bising suara rekaman walet yang ku putar pada sore hingga malam hari. Anaknya sulit konsentrasi belajar lah, suaminya yang capek pulang kerja jadi sulit tidur lah. Alih-alih ikut mendoakan agar semakin banyak walet yang menghampiri sarangku, mereka justru menyumpahi agar tak ada walet yang kembali.
Begitu pula dengan Pak Jaya. Rumahnya di sisi selatan. Dia mengeluhkan anaknya yang sakit flu tak kunjung reda. Dugaannya karena virus dari sarang burung ini. Aneh, padahal aku dan Sundari yang tinggal serumah justru sehat wal afiat. Flu anaknya pasti bukan karena sarang burung kami.
Aku jadi menduga, mungkin ketidakridhoan mereka akibat dengki dan prasangka sendiri juga ikut menyumbang turunnya omsetku akhir-akhir ini. Tapi Sundari langsung menepis pikiranku saat aku mengutarakan kepadanya.
“Ini kan lagi musim panas, Mas. Nanti kalau sudah masuk musim hujan juga walet-waletnya banyak lagi,” ujarnya menenangkanku.
Ah, sekarang aku kangen Sundari. Maklum, kami hanya tinggal berdua di rumah ini, selain ada walet-walet di lantai dua. Berbagai ikhtiar kami tempuh, tapi Tuhan belum juga mengizinkan kami mengasuh anak. Aku sampai bosan bercengkrama dengan Sundari. Sampai sarang-sarang burung ini juga kuajak bicara.
“Belum waktunya, Mas. Sekarang kita fokus membersihkan sarang-sarang ini dulu saja,” celetuk Sundari saat aku bertanya kapan kiranya kami dipercaya mengurus bayi darah daging kami. Dia mengatakannya sambil tersenyum. Jemari lentiknya gesit membersihkan sarang burung yang baru dipanen. Ada beberapa bulu halus walet yang masih menempel di sana. Sundari mengambilnya dengan pinset. Sementara aku merendam sebagian sarang burung lainnya ke baskom besar.
Sekarang aku berpikir lagi, sampai kapan aku bisa mengurung diri dengan tenang di kamar ini? Nanti malam ke-25 Ramadhan. Keluarga Mas Mudzil dan Mas Muhaimin biasanya mampir setelah puas mengantar anaknya jalan-jalan ke Malam Selawe. Mereka pasti membahas rencanaku mengalihfungsikan sarang burung walet jadi sarang manusia yang lebih ramah lingkungan, alias kos-kosan.
**
Sekarang pukul 19.00 WIB. Di balik jendela yang langsung menghadap gang di antara rumahku dengan Mas Muhaimin, aku menatap damar kurung bergelantungan. Cahayanya berpendar. Nyalanya menerangi gang di antara dua rumah ini. Juga gang antara rumahku dengan Mas Mudzil.
Bagiku, rumahku hanya satu, rumah warisan bapak untukku yang kini kutinggali bersama Sundari. Meski mereka memberikan kepadaku, aku hanya merawatnya, tidak menerima sepenuhnya. Lantai satunya rumah Cak Mudzil dan Cak Muhaimin aku sewakan pada penjual roti. Di satu sisi, aku bersiap kalau suatu saat nanti mereka ingin kembali. Syukur jika mereka membuka hati dan mau terjun mengelola sarang burung ini di hari tua kelak. Tentu bapak senang jika anaknya kompak mau melanjutkan bisnis warisan sarang walet.
Damar kurung itu sengaja aku nyalakan di malam Ramadhan ini. Biar anak-anak Mas Mudzil dan Mas Muhaimin senang kalau mereka jadi mampir. Sekaligus aku mencari hangat dan terang untuk menenangkan degup jantungku yang berdebar. Aku belum siap kalau harus menghadapi amukan mereka lagi. Sungguh aku menyesali keputusanku bercerita ke Cak Muhaimin dan Cak Mudzil. Mereka hanya menuntutku melangsungkan warisan itu tanpa peduli tantangan yang kuhadapi.
Hujatan dan cacian mereka kembali menggema. Anehnya, pesan bapak juga ikut-ikutan. Ramai bersahutan. Sungguh bising. Lemah sekali tetangga-tetanggaku yang terganggu dengan rekaman suara sriti dan walet yang kuputar. Mereka belum merasakan menjadi aku yang kini terus-menerus mendengar cacian saudara-saudaraku.
Suara itu kian mengeras seiring terang yang menyilaukan dari damar kurung di balik jendela. Aku tak tahan! Ingin ku bungkam mulut-mulut mereka. Kutempelkan dua telapak tanganku untuk menutup telinga, tapi tak berhasil. Suara itu tetap menggema. Ku sumbat telingaku dengan bantal. Masih sama.
Kepalaku semakin pening kala damar kurung itu berputar tersapu angin. Cahayanya sempat meredup seiring suara itu kian pelan. Tapi hanya sebentar. Kututup jendela kayu rapat-rapat hingga tak ada lagi cahaya damar kurung yang menerobos kamar. Ku padamkan lampu kamar hingga gelap gulita dan sunyi seketika. Aku berjalan gontai ke amben. Duh! Kakiku tak sengaja menyenggol cangkir kopi tadi pagi. Ampasnya langsung meluber ke piring. Sebagian juga ke lantai.
Dalam remang cahaya yang hanya berasal dari sela-sela lubang udara di atas pintu kamar, jariku menari di atas ampas kopi itu. Di piring, aku melukis wajah Cak Mudzil. Sedangkan di lantai, aku melukis wajah Cak Muhaimin. Rupanya segala emosi bisa ku luapkan dalam gelap. Entah bagaimana aku justru fokus melukis dua sosok yang membuatku geram dua hari ini.
“Mas Damar sudah tidur? Jam segini kok sudah gelap? Tumben, Mas….” Dari balik pintu, Sundari kembali mengetuk dan memanggilku. Aku mengabaikannya dan terus khusyuk menyalurkan segala emosi di lukisan ampas kopi ini. Tak peduli seperempat lantai area kamarku jadi penuh wajah cacakku. Lantai itu tak lagi berwarna merah pudar polos.
Rupanya darah seni ibu dalam melukis menurun kepadaku. Bakat yang tidak bapak sukai karena bapak benci melihat ibu melukis. Aneh memang. Begitulah keluargaku. Aku yakin bapak akan marah kalau melihat lantai kamarnya kulukis.
Tak cukup lantai, aku juga melukis wajah Pak Jaya, Bu Sabar dan Bu Rahman di dinding kamar yang sebagian sudah mengelupas dan berlumut. Dengan sisa ampas kopi tadi. Mudah sekali, tak butuh waktu lama hingga tergambar potret wajah mereka. Sungguh ini sebuah kenikmatan yang tak kutemukan saat memanen atau mengolah sarang burung walet.
Baiklah, Pak, maafkan Damar yang sudah durhaka dengan menodai kamar bapak. Bukankah Cak Mudzil dan Cak Muhaimin juga telah durhaka dengan sedari dulu menolak untuk merawat warisan dari bapak dan menyerahkan sarang burung mereka padaku?
Kalau memang ketiga sarang burung ini tak boleh diubah jadi kos-kosan, biarkan aku mencari hidup dari seni ampas kopi. Damar akan menunaikan pesan Bapak. Damar menemukannya!
Sayyidah Nuriyah. Kondisi pandemi Covid-19 membuatnya bertahan hidup dengan menekuni dunia kepenulisan. Perempuan kelahiran Gresik, 13 Juli 1996 ini semakin rajin menulis ketika menjadi Kontributor sejak 2019 hingga Coeditor PWMU.CO sejak 2022. Portal berita ini pun memberinya penghargaan juara I Penulis Terbaik 2022 dan juara I Penulis Terproduktif 2022.
Gang Sebelah
Yayasan Gang Sebelah didirikan pada Tahun 2017, sebagai bentuk upaya dalam melakukan penelitian, pengarsipan dan pengembangan Kebudayaan.