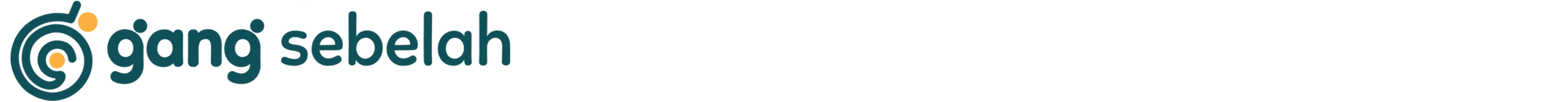Daratan ini dulunya sungguh luar biasa indah. Sebuah tempat yang menjadi kegemaranku setiap sore adalah pohon petai raksasa di ujung kampung. Tepat di atas bukit dengan hamparan bunga liarnya.
Selama tujuh tahun aku mengira tempat itu hanya milikku. Tidak pernah aku menemui seseorang mengunjungi tempat itu, selain aku sendiri. Mungkin karena jarak yang cukup jauh dari perkampungan.
Oi, tahukah kau betapa terkejutnya aku saat kudapati sosok manusia lain di sana? Dan yang paling mengejutkanku dia seseorang yang tak pernah kuduga sebelumnya.
“Ayung! Mau ke mana lagi? Sudah magrib,” kata mama di bingkai pintu rumah.
“Sebentar Ma! Kamera Ayung ketinggalan,” teriakku sambil melambai, menunjukkan punggung yang perlahan pergi.
Wah, jika saja kamera kecilku tidak ketinggalan di padang bukit, jika saja aku tidak ingat dan memaksa kembali ke sana, bisakah aku bertemu dia? Ribuan pertanyaan itu seakan ribut memaksa kepalaku menjawabnya. Padahal, harusnya mereka menyadari, bahwa otak, hati, dan sukmaku pun tidak pernah tahu.
Sesampainya di puncak bukit aku merasa tenggorokanku sekering padang gurun di Afrika. Ditambah reaksi terkejut saat mendapati siluet hitam di balik pohon petai raksasa itu. Oh, Tuhan! Kurasa aku melihat setan yang biasa diceritakan Mbah Kung tiap malam Jumat.
Tanpa kusadari neuron dalam otakku bekerja sendiri, ia mengirim sinyal secepat cahaya tanpa meminta izin pada sang tuan. Lebih bodohnya lagi, sinyal itu memaksa tenggorokanku berteriak sekencang-kencangnya dan membuat siluet hitam itu mendekatiku secara perlahan. Rasanya jantungku mau rontok dibuatnya. Bayangan itu mulai mendekatiku. Takut melihatnya, kututup rapat mataku.
“Kamu yang punya kamera ini ya?” Oh Tuhan, sejak kapan setan bisa bertanya dengan suara semerdu itu?
Tubuhku menggigil, tanganku berkeringat dingin, kupaksa mataku melihat wajah siluet itu. Sekali lagi, semesta membuatku terkejut. Apa yang kulihat ini adalah hadiah Tuhan yang tak pernah kusadari.
“Yung, aku mau kamu nulis tentang atlet. Blog kita harus diperbarui! Aku mau topiknya mengikuti apa yang lagi panas akhir-akhir ini. Jangan cuma bahas soal makanan, tempat sejarah, apalagi soal buku-buku. Itu sudah biasa!” celoteh Kang Madi.
Oh iya, aku belum cerita. Jujur, kisah ini dibatasi oleh daya ingatku. Kadang aku hampir lupa menceritakan tokoh yang sangat penting dalam kisah ini, salah satunya Ketua Komunitas Jurnalistik Ananta Dharma yang sudah berdiri sejak tahun 1999.Aku sendiri mulai nimbrung dengan komunitas ini sejak duduk di bangku kelas satu SMA, satu tahun yang lalu.
Kang Madi adalah salah satu orang yang paling aku segani. Gaya bahasa dan kreativitasnya sudah setara dengan jurnalis profesional Ibu Kota Jakarta. Aku senang bisa belajar banyak hal dari dia, tapi layaknya manusia bumi pada umumnya, Kang Madi masih suka memerintah orang lain.
Dia suka mengusik ketenanganku, padahal aku sudah memikirkan akan menulis apa minggu ini. Nggak ada angin nggakada hujan apalagi sampai ada petir, tiba-tiba minta aku meliput keseharian atlet kabupaten. Sesuatu yang tak pernah kulakukan sebelumnya.
“Yah, Kang, kok Ayung sih. Kan minggu ini aku mau menulis Problem Gelora Joko Samudro, Kang!”
“Terus siapa lagi yang mau nulis, Ayung?”
“Kan ada Chiko Kang.”
Chiko melirikku tajam tanda tak senang. Akhir-akhir ini dia sedikit temperamen, mungkin sedang melewati masa pubertas. Biasalah, remaja SMP, lagi alay-alaynya.
Detik itu juga aku menelepon Icun, salah satu temanku. Dia atlet bulu tangkis kabupaten. Temanku sejak sekolah dasar.
“Kapan kalian bisa diwawancarai, Cun? Coba tanya pelatihmu!”
“Kamis pagi, awakmu iso kan?”
Seperti kata Icun, Kamis pagi aku bertolak ke gedung olahraga di Jalan R.A. Kartini. Tempat di mana orang-orang dengan tubuh kekar dan ambisi besar itu berlatih. Di sana ada banyak latar belakang atlet bulu tangkis. Ada yang pernah juara PON, ada pula yang pernah bergabung menjadi anggota tim nasional, tapi putul di tengah jalan. Coach Arbi menjabat tanganku.Mempersilakan aku menunggu anak didiknya sampai interval istirahat tiba. Beliau pelatih yang ramah, tapi tegas. Aku bisa melihat dari raut wajahnya.
“Makasih, Coach,” ucapku singkat.
Icun dengan jersey merah menyala melambaikan tangan dari kejauhan. Melirik ke arah jarum jam pukul empat di sebelah kiriku. Kode supaya aku duduk di situ.
Tanpa sadar aku mulai memperhatikan tempat ini. Menyapu setiap sudut gedung olahraga yang superkeren. Bau keringat seakan sama dengan bunga melati di sini. Tapi, satu hal yang membuatku sedikit tersipu. Laki-laki dengan jersey biru, memegang raket Yonex edisi terbaru milik sang juara All England. Raket dengan harga setara makan nasi krawu khas Gresik selama setahun.Sangat keren.
Perlahan aku memperhatikan dia dengan saksama. Otak kecilku mencoba mengingat di mana aku pernah melihatnya. Oi, bukankah itu manusia siluet, si setan hitam yang kutemui di bawah pohon petai kemarin? Kenapa dia di sini?
“Saya Sigi Budikusuma,” kalimat pertama keluar dari mulutnya. Lidahku berkelu.
“Aduh, Gi, nggak usah terlalu formal lah! Dia seumuran kita kok, santai wae! Yo kan Yung,” sahut Icun, memotong si siluet hitam yang barusan aku ketahui namanya. Sungguh indah, Sigi berarti kemenangan, Budikusuma berarti berbudi luhur layaknya kusuma bangsa, bunga segala bunga.
Dia perlahan mengulang kalimatnya, aku melihatnya dengan saksama. Tangan kananku yang memegang audio recordsedikit terguncang, mungkin dia malu.
“Namaku Sigi Budikusuma, atlet bulu tangkis Gresik. Sekarang masih fokus sama pertandingan minggu depan, Sirkuit Nasional,” jawabnya sambil mengangguk pelan, tanda memintaku melanjutkan pertanyaan.
Ah, ternyata dia salah satu atlet yang dijagokan di sini. Keren, sungguh keren. Wawancara kumulai. Dan, semakin detik berdetak, dia semakin keren.
Aku menutup sesi wawancara kali ini dengan meminta seluruh atlet kabupaten berfoto bersama. Para manusia keren itu terlihat luar biasa di mata kameraku, tapi hanya satu yang paling bersinar di mataku: si ringkih sang siluet hitam.
“Jadi kamu anggota klub jurnalistik itu ya? Pantas foto di kameramu bagus-bagus. Sengaja aku melihatnya kemarin. Awalnya cuma mau memastikan kamera siapa itu. Tapi fotonya luar biasa, aku kira yang punya itu penggila fotografi. Niat banget ambil gambarnya,” jelasnya sambil menenteng tas hitam biru bertulisan Yonex yang sungguh besar.
“Ah iya, sudah satu tahun terakhir aku ikut klub itu. Oh iya Sigi, soal yang kemarin aku minta maaf ya. Aku kira kamu setan, habisnya kamu tiba-tiba muncul di balik pohon petai itu. Selama ini aku nggak tau kalau ada orang lain yang ke sana.”
Satu hal unik lain yang aku ketahui sejak bertemu Sigi malam itu. Sama seperti aku, dia selalu di sana. Bedanya, aku mengunjungi bukit itu setiap sore menjelang senja, dan dia setiap senja menjelang malam. Jadi, ketika aku pulang, dia datang.
Tuhan dan semesta memang menyimpan banyak rahasia. Dan, satu rahasia-Nya sudah berhasil aku pecahkan. Malam ini kami berdua duduk bersama di bawah pohon petai raksasa dengan sinar bulan yang cahayanya tidak sehangat mentari. Tapi,sepertinya anak Adam di sampingku yang membuatnya hangat. Ah, kisah cinta masa remaja.
Sejak hari itu, aku selalu semangat jika diminta meliput soal atlet. Terutama atlet bulu tangkis kabupaten. Aku sangat berterima kasih pada Kang Madi. Berjuta kali aku mengatakan cinta padanya.
“Kang, hari ini nggak onok jadwal ngeliput atlet lagi ya?” tanyaku sambil menyeruput teh manis buatan Chiko.
“Gak onok, Yung. Ngenteni mereka menang Sirnas dulu baru kamu ngeliput lagi!”
“Kang, kalau Ayung ikut mereka yaopo? Langsung meliput di Sirnas. On the spot, Kang,” tanyaku antusias.
“Ngawur kon! Siapa yang menemani kalau berangkat sendiri?”
“Ya, kalo berangkat sendiri yo gaonok sing ngancani Kang.”
“Jangan aneh-aneh! Mrono iku nganggo duit, ora nganggo godhong.”
“Gak asyik sampeyan iku, Kang.”
Sigi tertawa mendengar ceritaku. Oi, aku lupa lagi. Kini, setiap senja menjelang malam kami bertemu. Aku menunggunya pulang latihan dengan antusias. Sejak saat itu si setan hitam selalu menemaniku setiap malam. Tujuh belas tahunku ternyata sangat indah. Amboi!
“Semangat ya, Gi! Minggu depan kamu tanding. Jujur, aku mau lihat kamu tanding secara langsung,” ujarku sambil memandang matanya yang kelelahan.
Seperti biasa Sigi selalu tersenyum. Dia sangat pandai menyimpan perasaannya. Dia tidak pernah tahu, bahwa dari matanya aku bisa menebak setiap rasa yang ia lahirkan. Saat dia senang, sedih, cemas, lelah, bahkan saat ia bosan dengan ambisinya. Aku tidak pernah memaksa ia bercerita. Selalu kubiarkan seperti ini, mengalir seperti tenangnya Bengawan Solo.
Hari ini Sigi pergi, ia berlari lebih jauh. Pertandingan itu adalah segalanya. Jika dia menang, bukan tidak mungkin PBSI akan memanggilnya. Istana bulu tangkis termasyhur di negeri ini.
Malam hari kini terasa sepi, tapi aku tahu sang penunggu pohon petai tengah berjuang di bawah lampu sorot dengan senjata besi berongga andalannya. Aku bisa membayangkan teriakan kencangnya saat berhasil menaklukkan satu poin lawan lewat smes kencang milik Taufik Hidayat yang ada pada dirinya. Tiap selesai bermain dia meneleponku. Mengabarkan dengan suara tersengal-sengal, namun penuh ledakan kemenangan.
Tapi, ada yang berbeda malam ini, dia tidak menelepon.
“Mbak Ayung! Mbak, dipanggil Kang Madi.”
“Iyo sebentar,” sahutku.
“Sekarang aku kasih kamu tugas yang paling luar biasa. Pergilah ke gedung olahraga!”
Tanpa pikir panjang. Kusambar kamera, catatan kecil, dan pulpen setiaku sambil berlari menuju tempat keramat itu. Tempat yang sudah mengajarkan banyak hal pada Sigi kecil hingga ia tumbuh menjadi atlet yang galak di umur tujuh belasnya. Aku cemas, apakah dia menang atau kalah? Apa pun, asalkan dia kembali.
“Ayung,” aku menoleh ke arah suara itu. Ah, bukan Sigi.
“Cun, bagaimana? Atlet kita ada yang menang?”
“Ditunggu Sigi di tempat biasa katanya.”
Meski pertanyaanku tak dijawab, aku tidak marah pada Icun. Kaki kananku berbicara pada temannya, si kaki kiri. Memintanya untuk segera berlari. Di pikiranku saat itu, hanya dipenuhi Sigi. Aku membayangkan dia dengan medali emas di lehernya, buket bunga di tangan kanan, dan piala di tangan kiri, sambil tersenyum lebar ke arah kamera. Kurasa, aku memiliki bakat menjadi pelari kalau begini.
Di bawah pohon petai raksasa itu, penunggunya sudah kembali. Duduk bersila, sambil menatap langit. Lagi-lagi jerseybiru yang ia pakai. Aku duduk di sampingnya, dia menoleh ke arahku pelan. Seperti biasa, ia menunjukkan senyumnya padaku. Oi, senyum apa ini? Apakah dia gagal? Oh Tuhan, haruskah aku mulai menghiburnya?
“Kenapa nggak tanya bagaimana pertandinganku?” ujarnya memulai percakapan.
“Kenapa kamu nggak cerita bagaimana pertandinganmu?”
Lagi-lagi dia tersenyum.
“Sejujurnya aku merasa senang, tapi juga sedih. Pertandingan final malam itu, rubber 1 jam 36 menit. Pertandingan terlama yang pernah aku lakukan. Di set kedua aku mulai kelelahan. Rasanya aku ingin biarkan dia menang. Tubuhku menyerah padanya,” keluhnya.
Ia menarik setengah napas, lalu mulai mendengus lagi, “Tapi entah mengapa, tiap aku memutuskan berhenti kamu selalu datang, Yung. Di mataku. Dan, itu yang buat aku berdiri di podium paling tinggi, aku berhasil membawa pulang medali emas pertamaku.”
Aku bahagia, sungguh sangat bahagia.
Pagi ini sepertinya membuatku sadar. Bahwa selain bahagia, ada rasa lain yang sedang main petak umpet dengan hatiku. Dia si sedih yang malu-malu.
Aku tahu, jika Sigi menang di pertandingan itu dia akan pergi. Meninggalkan masa remaja kami di sini. Sungguh kasihan pohon petai raksasa akan kehilangan penunggu malamnya untuk waktu yang lama. Dan, apa kabar kau, Hatiku? Yang penunggunya juga akan pergi.
Meski sulit, aku paksa hati ini melepasnya. Biarkan dia mengejar impiannya. Entah berapa tahun yang akan datang aku bisa melihatnya membela kebanggaan yang sangat ia kagumi. Entah aku akan mendengar teriakannya di radio, melihat wajahnya di televisi, atau mungkin merasakan atmosfer yang sama dengannya di lapangan. Selamat tinggal, si siluet hitam, sampai bertemu di Istora.
* * *
Wah, waktu berlalu begitu cepat. Sekarang aku sudah menjadi seorang mahasiswa, merantau jauh ke Ibu Kota Jakarta. Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia menjawab panggilanku.
Amboi, indahnya belajar di sini. Sama seperti masa remajaku dulu, aku masih menjadi seorang penanti yang profesional. Orang yang sama, rindu yang sama, dan hati yang sama. Bedanya tempatnya sekarang bukan di bawah pohon petai raksasa di ujung kampung, tapi di bawah atap UI, di depan proyektor raksasa.
Hari ini aku memutuskan mengunjungi Cipayung, supaya bertemu lagi dengan si siluet hitam. Dua puluh tahun usia kita, dan selama bertahun-tahun kita berpisah. Meski tidak segalau kisah Hayati dan Zainuddin, tapi kisahku hampir sama. Jika Hayati menikah dengan lelaki lain, berbeda dengan Sigi. Dia menikah dengan raketnya. Wah, sungguh iri.
PBSI ternyata sama seramnya dengan film horor yang pernah kutonton di bioskop. Aku ditolak mentah-mentah. Tidak boleh masuk.
Oi, tidak tahukah mereka siapa aku? Ya memang bukan siapa-siapa. Tapi setidaknya aku masih seseorang yang merindukan sosok hebat yang kukenal di dalam istana bulu tangkis itu. Jahat sekali tembok ini memisahkan kami.
Tidakkah kalian penasaran bagaimana akhir kisah ini? Jangan tanya padaku, apalagi memintanya menuliskan untuk kalian. Jujur, aku sendiri masih bingung.
Memang benar bahwa kisah cinta yang dituliskan bagaikan air yang mengalir, tidak akan ada ujungnya. Dulu aku berpikir Bengawan Solo itu selalu tenang airnya, seperti kisah Sigi dengan ambisinya. Tapi, bodohnya aku, bahwa Bengawan Solo juga pernah marah. Entah pada manusia atau pada yang lainnya.
“Sigi Budikusuma? Nggak ada nama itu, Yu. Gue taunya Alan Budikusuma,” ucap salah satu temanku, kakaknya juga atlet bulu tangkis Pelatnas.
“Ada kok, dia yang menang Sirnas tiga tahun lalu. Masa tidak ada? Coba kamu tanya kakakmu lagi lah.”
“Benar nggak ada Yu. Sudah berapa kali gue jelasin.”
Luar biasa sekali, baru kutahu kalau kata ‘tidak ada’ itu sungguh menyakitkan. Lebih sakit daripada suntikan difteri petugas UKS di SMA dulu.
Berhari-hari aku mencari informasi soal Sigi. Menelepon ke sana dan kemari. Entah berapa kali aku mengunjungi agen penjual pulsa di sebelah kos yang terletak di Jalan Mangga Muda. Kini tinggal satu orang yang harus kuhubungi. Icun, kamu harus bilang semuanya.
“Kok tega kamu, Cun, menyembunyikan hal itu selama ini. Tego kon! Kenapa kamu nggak cerita, kalau dia…” Tiiittt…telepon genggamku terjatuh, air mataku juga jatuh. Besar-besar, seperti biji jagung.
Malam ini sepertinya semesta membuatku sadar, bahwa aku tidak sepenuhnya mengenal sang penunggu pohon petai, aku tidak bisa menebak perasaannya. Kalau saja, malam itu aku melihat kakinya. Kalau saja aku tahu dia terluka. Kalau saja aku menyadari pertandingan malam itu menjadi final terakhir baginya. Kalau saja aku tahu, Sigi terluka.
Berjuta kali, aku menyalahkan diriku. Jika bukan karena ujian semester, aku pasti pulang detik ini juga. Wah, luar biasanya skenario Tuhan, hebatnya sang alam menyembunyikan kecemasan.
Kini aku tahu kenapa Zainuddin memutuskan menulis saat Hayati pergi, bukan hanya karena ia berbakat. Tapi, dengan menulis Zainuddin bisa marah pada semesta. Hanya dengan menulis, hatinya terobati. Dan, hanya dengan menulis, dia bisa mengadu, walau untuk sementara.
Satu bulan yang berganti menjadi tiga, aku pulang. Kereta api kelas ekonomi Jakarta-Surabaya, dilanjutkan angkot Pasar Turi-Gresik, dan berakhir di tanah yang sama. Tanah masa remajaku yang dipenuhi bunga liar.
Ternyata, pohon petai raksasa itu tidak ditinggalkan tuannya. Justru akulah yang bodoh, mengira dia pergi. Seseorang dengan punggung yang sama, duduk di sana. Bedanya, tidak hanya malam ia menghibur sang pohon. Kini pohon petai raksasa itu sepertinya bosan selalu dikunjungi sang tuan. Tiap pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh, dan pagi lagi sang penunggu selalu datang saat hatinya ingin berlabuh.
Mengapa Tuhan menciptakan air mata yang jatuh pada momen kesedihan manusia? Satu pertanyaan itu tidak bisa kujawab hingga saat ini. Sama seperti mengapa Tuhan membuat dia sakit pada momen paling luar biasa yang dia punya? Dan yang paling menyakitkan, mengapa Tuhan ciptakan rasa putus asa di hati manusia?
Hari itu aku melihat si siluet hitam pasrah, titik paling lemah dalam hidupnya. Kini tak bisa lagi kulihat dia terbang, apalagi melihatnya dengan backhand andalan. Aku hanya mematung di balik pohon petai raksasa itu. Kaki kananku kini diam, dia tidak sesemangat dulu. Begitu juga dengan kaki kiriku. Kami seperti lagu milik Tulus, seorang solois. Tubuh kita saling bersandar, tetapi menghadap ke arah mata angin berbeda.
Satu menit yang berganti menjadi satu jam. Kami sama-sama diam. Tapi, semesta kali ini berbuat curang. Tadinya aku yang ingin bersembunyi dibuatnya ketahuan. Petak umpet yang paling kubenci dalam dua puluh tahun hidupku.
Sigi sang pemilik segala ambisi, kini berdiri di hadapanku. Bedanya, ia tidak sekekar dulu. Dia bahagia dengan kisahnya sendiri. Kisah yang jauh dari mimpinya, jauh dari bahagia yang menjadi harapannya. Mata itu mengatakan segalanya.
Untuk kamu yang membaca kisah ini, seperti halnya Sigi aku harap kamu bisa merasakan kisahmu sendiri. Ya, benar sekali. Mungkin Sigi gagal menjadi pebulutangkis nasional. Tapi, dia tidak pergi meninggalkan sang pohon petai raksasa. Dia tetap tinggal dengan perlahan menghidupkan kisah pilunya menjadi bahagia yang sesungguhnya. Dia memilih jalan yang berbeda,jalan yang dibuatnya sendiri dengan rumahnya. Tapi aku yakin dia bahagia dengan pilihannya.
Tangan kananku mengait di lengan kirinya. Menghitung bintang yang berdesak-desakan.