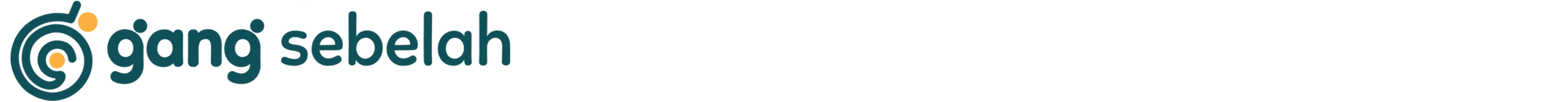Aku terpikat. Sekali-dua matamu mengerjap. Bibirmu, entah keberapa selalu bergerak tak teratur. Seperti mengucapkan kata yang tak pernah ku pahami. Tadi, sebelum kau berbaring dengan kaki meringkuk, memandangiku kosong. Hampa. Seperti seekor ngengat memandang ke arah luar setelah membentur-benturkan diri dari balik kaca jendela. Aku sempat menggerai putih rambutmu yang legam itu, seperti semesta lain dalam kepala.
Di luar, hujan mengguyur. Dingin pelan-pelan menyergap. Dan kau, seperti bersusah-payah terlelap. Aku mencoba melempar pandang, dari celah pintu yang tidak tertutup sempurna, tempias cahaya dari lampu jalan menerangi halaman. “Lupakan hari itu, lupakan. Seperti upaya kau mengenangku,” pelan aku bergumam. Suaraku seperti menyaingi lalu-lalang kendaraan yang terus bergegas. Sungguh, aku tak hendak membencimu. Sama sekali.
Sekarang sudah tengah malam, dan harusnya kantuk menyerang. Tetapi, kelopak mataku terus menyala. Dan tubuhku sedikit menggigil. Aku seperti dikerubungi masa lalu, yang muaranya ada di punggungmu. Pelan aku menoleh, kau sungguh terlihat sayu. Dan badan sintalmu meranggas. Siapa yang berani menggerogoti usiamu? Aku tak percaya betul, seseorang yang kukenal belasan tahun silam menjadi sedemikian menyedihkannya. Dari seorang gadis menyenangkan yang berapi-api dalam berujar, dulu sejauh dua kilometer dari badukan ikan Kecamatan Lumpur, sebelum jalan Sindujoyo, beberapa saat setelah kau dengan sumringah memandangiku dari bale keling itu, telah menguar aroma pekat laut. Aroma yang menguasai dada dan kepala. Aroma yang setengah mati kau banggakan.
Dan sekarang, di tempat tidur yang gampang berderit jika kau tiba-tiba menggeliat itu, kau hanya serupa manekin dengan nadi berdenyut. Hidup. Tetapi hampa. Satu-satunya, barangkali, yang melekat dari tubuhmu adalah ribuan kenangan yang terus menusuk jantung dan hatimu. Bibir juga matamu. Tetapi jujur aku tersanjung. Kamar tua dua lantai dengan langit-langit tinggi ini, masih menyimpan sepasang kursi kayu jati dengan ornamen khas Holland. Kau tak menggeser apapun barang sesenti pun. Kau menghargai kenangan bukan? Kau betul-betul gadis penurut.
Kepalaku tiba-tiba pening. Aku meraih sebungkus rokok lalu menyulutnya. Asapnya mengepul, seperti sepasang cerobong kereta api tua. Aku kemudian terhanyut. “Manisku, kenapa dunia hanya seumpama reruntuhan kesedihan yang dengan wajar kita bangun saat masa remaja?”
Aku bangkit dari duduk tetapi tubuhku tetap menggigil. Hujan sudah reda. Dan angin seperti terus berhamburan dari celah pintu dan jendela. Aku pandangi tubuhmu kesekian kali, dan kurasa tidurmu malam ini tak nyenyak. Kau terus menggeliat berkali-kali. Sepekan lalu, sebelum aku bersiap mengunjungimu setelah belasan tahun, aku mengunjungi kawan lamamu di sebuah gang dekat warung Awi, warung kopi legendaris yang harumnya hampir selalu menggedor-gedor kenangan ini. Dari dia aku segera tau, hampir tiap petang setelah semburat mega mulai lenyap dan burung-burung yang katamu dulu menyerupai camar terbang ke selatan, kau selalu mengunjungi stasiun itu. Duduk di dekat peron dengan kaki menjuntai dan menatap jauh ke barat. Tanganmu sesekali melambai berharap ada seseorang menghampiri. Berharap aku yang pengecut ini menepati janji.
Aku gontai berjalan ke jendela dan membuka engselnya separuh. Dari sini, katamu suatu kali, dapat memandang lanskap pelabuhan. Kota bagian timur laut yang selalu terlihat mengiba. Aku sedikit menyunggingkan senyum. Kau tau, kadang-kadang masa depan tak hendak memungutmu. Kadang-kadang, ia hanya membiarkanmu menyentuhnya sedikit tetapi tetap membiarkan tubuh dan seisi kepalamu berenang dalam semesta masa lalu. Aku rasa, hal itu yang menggerogotimu. Seolah kau dan kesedihan adalah sepasang.
***
Stasiun Grisee, 11 April 1967. Pukul 06. 12 AM.
Hari melambat. Sepagi itu, orang-orang telah berkerumun. Di pelataran stasiun, berjejer penjual segala macam makanan. Aku sedikit berjinjit lalu memicingkan mata ke arah papan informasi dekat ruang loket, ternyata pemberangkatan paling pagi kereta api menuju stasiun Sumari masih dua jam lagi. Dengan sedikit kikuk aku pelan-pelan mencari makanan apa yang hendak memuaskan hasrat perut.
Di sudut kanan stasiun, beberapa depa dari warung kopi kecil tepat di dekat pohon asam yang menjulang, ada seorang perempuan paruh baya penjual Sego Roomo, makanan khas mirip bubur dari desa Romo, Kecamatan Manyar, Gresik. Makanan khas setempat, bagiku, selalu memuaskan. Setelah memesan seporsi, aku menghidu pelan-pelan. Seketika aroma meresap dan kenangan-kenangan pendek dari kota ini bermunculan.
Pagi sungguh-sungguh melambat. Aku sedikit menoleh ke utara, dan dari sana, pada dinding ruang loket, ada jam berukuran besar menggantung. Sebentar lagi, aku akan terlempar dari tanah ini. Hanya sebentar lagi. Mengapa kau belum muncul-muncul juga? Aku pandangi sekitar dengan gamang. Sejak kerusuhan tahun lalu, dan kabar buruk yang terus susul-menyusul dari ibu kota jauh sana, aku tak hendak memilih apapun. Selain berupaya mendengarkan baik-baik petuah orang tua.
Aku gelisah. Kupandangi saja tiga gerbong kereta yang mangkrak dengan setengah gugup. Suara orang-orang membaur dari segala arah sedikit memecah ketertarikanku. Rupanya, setelah lebih dekat, gerbong mangkrak tersebut menguarkan aroma besi tua yang kuat. Mirip mesiu, kataku. Bekas gerbong itu, yang kaca jendelanya telah pecah, telah dijalari beragam tanaman liar. Dan sedikit ruang dalam gerbong yang dekat pintu telah dijadikan oleh beberapa penjual untuk menggelar dagangan. Tetapi kau tau, bahkan meski sebuah ruang telah beralih fungsi, kenangan-kenangan di dalamnya tetap berhambur.
Lewat cat biru tua yang terkelupas, pada bingkai jendela yang hampir tidak dikenali itu, aku mengingat banyak hal. Dulu, sewaktu remaja, Abah pernah jatuh setelah buru-buru ingin menjemput seorang kiai dari Madura yang kebetulan ingin sekali berziarah ke makam Nyai Ageng Pinatih. Abah terburu-buru sampai kepalanya membentur gerbong saat berdesakan menaikinya. Hatiku sendu. Saat-saat begini, jadi mengingat banyak hal. Kemudian perasaan selanjutnya adalah was-was. Aku berangkat ini juga karena Abah. Sebab kerusuhan itu, sebab kiai yang kami takdzimi wafat.
Matahari mulai menggelinding. Terdengar riuh dari pojok stasiun. Agaknya, stasiun kecil ini akan meruah saat-saat begini. Dari jauh, suara Lokomotif Uap bergigi E1060 melengking. Suaranya, terdengar semacam rintihan kecil dan terus membesar. Seperti kesedihan yang aku tanggung dan lama-lama membiak. Kau di mana, sudah dekat waktu akan menyeretku pergi. Sudah dekat hari yang akan kita kecualikan dari langit menimpa. Apa kau tak ingin melepasku untuk terakhir kalinya?
Pelan aku seret tubuh menuju loket karcis dan memesan kereta menuju stasiun selanjutnya dan selanjutnya. Sebelum petugas meneriaki dengan galak. Sebelum orang-orang berkerumun lebih banyak. Sepasang mata yang gemar memandangimu ini telah hampa dan nelangsa. Sungguh, jika bukan sebab Abah, tak akan kupedulikan seru-seruan petugas yang menjengkelkan itu. Sungguh aku ingin terus di sini, menemuimu untuk terakhir kalinya.
Setelah memesan tiket kereta, dan bergegas masuk di gerbong ketiga, akhirnya aku sadar kau tak akan pernah ingin menemuiku. Dan aku, harus bersiap melepas segala macam hal dari hidup. Aku duduk di baris kedua dekat jendela. Ah, kau tau, secepat apapun kereta ini akan melaju nanti, perasaanku tentang kampung kita, pada kota kecil pinggir Jawa ini, tak akan pernah selesai berdengung dalam kepala.
Tepat di sampingku, seseorang dengan pakaian khas orang terpandang sedang mengenggam sebuah koran. Aku tiba-tiba tertarik ikut membaca. Setelah mencoba melirik, akhirnya aku segera tau pada tajuk berita, telah terjadi huru-hara dua tahun terakhir. Presiden pertama tumbang, dan Soeharto, panglima tentara kita itu menggantikannya. Ia menyeru-nyeru dan mengutuk orang-orang yang tertuduh Pe-Ka-I dimusnahkan. Sungguh wajahku pias. Jantungku memburu. Sewaktu itu, aku sudah membayangkan banyak hal buruk akan menimpa tanah air kita.
***
Malam semakin larut. Aku merapatkan jaket dan memandangimu sekali lagi. Bahasa apa yang paling pas untuk menggambarkan kesedihanku? Mataku tiba-tiba basah. Merembes. Sebagai laki-laki pengecut, aku hanya dapat menertawakan masa silam dengan getir. Dan kau, perempuan dengan sepasang kenangan yang terus berhamburan dari punggung dan kepala menanggung semua hal seutuhnya. Kau menggemari apa setahun terakhir? Ringan aku tersenyum dan pelan-pelan mendekati ranjang lalu duduk disampingmu. Lalu berusaha merebahkan diri.
“Aku mencintaimu, sungguh,” pelan aku bergumam.
“Apakah kau dapat memaafkan segala kesalahanku?,” ujarnku, sekali lagi.
Tidak ada suara. Hanya angin yang terus susul-menyusul meningkahi jendela.
***
Pembaca yang baik, seperti cerita klise lain. Seperti hal-hal buruk dari hidup, sebagai pengarang, saya ingin menceritakan potongan kisah kecil yang tak diceritakan tokoh utama kita. Sebulan setelah tokoh utama kita berangkat dari Stasiun Grisee, peperangan meletus sekali lagi. Slogan Ganyang Pe-Ka-I menjadi semacam petuah yang tidak siapapun bisa menolaknya. Ia, tokoh utama kita yang baik itu, ikut dalam barisan pembasmi. Dan ditugaskan menyisir antek-antek Pe-Ka-I di Gresik dan sekitarnya.
Kalian tau, pembaca yang baik, keluarga kekasih dari tokoh utama kita adalah loyalis Pe-Ka-I yang berpengaruh di Kabupaten Gresik dan sekitarnya. Dan dari moncong senapan tokoh utama kita itu, riwayat keluarga kekasihnya berakhir. Tidak, tidak. Pembaca yang baik tidak usah bersimpati berlebihan. Meski kita tahu, kekasihnya yang menyaksikan pembantaian itu dengan mata kepala sendiri akhirnya menjadi murung dan gila. Menjadi kehilangan segala hal dari hidup.
Tetapi bukankah begitu dunia bekerja. Hanya menciptakan ribuan kesedihan yang terus berhamburan dari balik kenangan-kenangan? Bukankah begitu, wahai pembaca yang baik. Sebuah kota terus disusun dari ribuan penderitaan-penderitaan yang mengharukan. Tetapi seperti apapun kota berdiri, kenangan-kenangan pendek yang telah menjelma harus terus diingat sepanjang masa.
Yogyakarta, 2023
*untuk seorang nenek renta, yang saya temui ketika menelusuri stasiun Grisee.
M. Rifdal Ais Annafis. Peserta Residensi Literatutur yang diselenggarakan Yayasan Gang Sebelah bekerja sama dengan Kemdikbudristek di Gresik (2023). Buku puisinya, Artefak Kota-Kota di Kepala (2021) dan tulisannya terpublikasi di pelbagai media seperti: Koran Kompas, Tempo, Suara Merdeka, Media Indonesia, Lombok Pos, Harian Sultra, Harian Merapi, Sabah Exspres Malaysia, dan lainnya. Juga memenangi sayembara penulisan seperti Payakumbuh Poetry Festival (2021), Festival Bulan Bahasa & Sastra Universitas Negeri Semarang sebagai juara pertama, Festival Bahasa & Sastra Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka Jakarta sebagai juara kedua, dan lainnya. Ia sekarang berkegiatan di Komunitas Kutub Yogyakarta Bisa dihubungi via: 081515316198 (WA) dan Instagram @mrifdalaisannafis.
Residensi Literatutur mengundang 18 Penulis di Indonesia untuk diundang ke Gresik dalam upaya melakukan pembacaan, penggalian ide, dan menemukan gagasan atau kemungkinan lain yang kemudian dituangkan dalam cerita pendek. Residensi ini diadakan oleh Yayasan Gang Sebelah yang didukung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Gang Sebelah
Yayasan Gang Sebelah didirikan pada Tahun 2017, sebagai bentuk upaya dalam melakukan penelitian, pengarsipan dan pengembangan Kebudayaan.