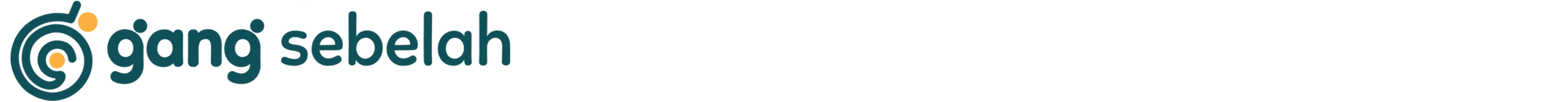Manusia adalah makhluk yang paling gampang untuk diperdaya. Terkadang aku hanya bergelayut manja di kakinya, lalu tangannya akan mengelus kepalaku sayang dan menggendongku. Di lain waktu aku mengeong merdu di depan kabinet dapur – yang aku tahu merupakan tempat di mana manusia itu menyimpan makananku, lalu makanan akan segera tersaji untuk kunikmati. Seperti pagi ini, manusia itu memberiku biskuit ikan yang terlihat mirip sekali dengan kerikil untukku buang air, namun berbau amis sedap penuh nutrisi.
“Ndut!!!” panggil manusiaku setelah usai mengisi mangkok makananku membuatku menghampirinya. Tangannya mulai membelai kepalaku saat aku menikmati makananku dan berkata dengan sayang, “Biasanya aku akan bilang “cepat besar”, tapi aku harus berhenti. Kamu terlalu cepat besar, Ndut.”
Aku menikmati makananku dengan hikmat. Biskuit ikan ini selalu enak, namun saat malam nanti seperti malam-malam sebelumnya, dia akan memberiku makanan basah berbau amis yang lebih nikmat dari seribu biskuit ikan. Dia menyebutnya ikan kaleng. Ikan itu bisa saja merupakan tuna, salmon, makarel, atau campuran ayam dan tuna. Suatu waktu dia mengajakku menonton ikan itu di layar gawainya yang lebar di kamarnya yang nyaman. Bentuknya berbeda dari yang biasa kumakan: utuh dan seperti makhluk hidup lainnya, memiliki mata dan mulut di kepalanya. Dari gambar bergerak yang kutonton di layar gawai lebar manusiaku, makananku yang bernama salmon berenang di hilir sungai menuju laut sedangkan tuna berenang berkelompok di laut. Mulutku berair melihat mereka tertangkap jaring nelayan. Manusiaku bilang ikan itu akan diolah untuk menjadi makanan manusia dan makanan untukku. Mereka akan dibawa ke tempat produksi: Pabrik, dengan P kapital sebagai perpanjangan tangan kapitalisme, jika aku ingin terdengar seperti kucing cerdas. Entah apa itu kapitalisme. Aku hanya mendengarnya dari berita televisi yang ditonton manusiaku sehabis bekerja. Dalam pikiranku selama kapitalisme mengolah ikan-ikan itu agar siap tersaji dalam mangkok makanku, aku akan menyantapnya dengan lahap.
Aku tahu aku dan manusiaku tinggal di kota yang penuh dengan Pabrik. Aku juga tahu manusiaku kerja di salah satunya. Setiap pagi, dengan mengenakan seragam dan helm pengaman berwarna putih, dia berangkat menuju apa itu yang disebutnya Pabrik. Setiap pagi pula aku mengantarnya sampai ke depan pintu dan melihatnya sejenak menyapa tetangganya. Basa-basi dimulai dengan pertanyaan retoris ‘Pergi ke Pabrik, Mas?’ lalu dilanjutkan dengan bahasan tentang naiknya iuran bulanan komplek dan matinya air PAM beberapa hari ini. Kemudian telingaku bergerak saat mereka membicarakan topik tentangku.
“Kucing ras, Mas? Anggora?” ucap manusia tetangga dengan sapu yang masih dipegangnya. Ujung sabutnya yang terombang-ambing ke kanan dan ke kiri membuatku ingin menerjangnya.
“Bukan, Bu. Ibunya kucing kampung biasa kok,” sanggah manusiaku.
Manusia tetangga itu tampak sangsi. Dia mungkin salah satu dari banyak orang yang menganggap semua kucing yang terawat dan berbulu panjang adalah anggora. Namun pergi ke dokter hewan beberapa kali dalam sebulan dan bulan-bulan berikutnya ketika aku masih kecil membuatku mengerti bahwa banyak sekali jenis kucing. Bagaimana dengan jenisku? Aku hanyalah kucing blasteran yang terawat saja. Sementara aku mulai bermain dengan ujung sabut sapu yang dipegang oleh manusia tetangga, ia mulai bertanya lagi, “Wulune apik, Mas. Oren alus kaya sulak ngunu. Lemu pisan awake. Mesti bapake kucing ras. Biasa ditinggal ngene ta?”
“Nggih, Bu,” jawab manusiaku singkat dan seperti tidak ingin memperpanjang pembicaraan, ia berkata sambil lalu seraya mengendarai motornya, “Monggo, Bu.”
Manusia tetangga itu melengos tak percaya, mencoba melepaskan sapunya yang kupeluk erat, menepuk pantat gendutku, lalu masuk ke dalam rumah, tak membalas pamit karena sudah pasti tak terdengar oleh manusiaku. Kehadirannya digantikan oleh manusia lain yang keluar dari pintu yang sama, manusia tetangga itu masuk, berpakaian seragam dan memakai helm yang sama seperti manusiaku. Tak seberapa jauh dari rumah, kulihat manusia-manusia lain juga sedang bersiap-siap akan berangkat kerja, mengantar manusia-manusia kecil ke sekolah, dan membersihkan rumah. Pagi. Waktu sakral bagi hamba Tuhan untuk pergi mencari penghidupan.
Salah satu dari manusia-manusia itu menghampiriku. Dia tidak berseragam, bukan salah satu dari manusia-manusia Pabrik. Aku mengenalinya sebagai anak laki-laki manusia tetanggaku tadi. Dia baru lulus dari sekolah tinggi dan pekerjaannya saat ini adalah memelihara burung kenari. Aku tahu itu karena aku tak sengaja mendengar ibunya menggerutu saat aku bermain-main dengan kenarinya. Saat itu, aku memanfaatkan kelengahannya menjaga kenari dalam sangkar itu. Kelengahan sesaat karena dia tengah hikmat menunduk seraya berpura-pura menyesali hidupnya saat Sang Ibu memarahinya. Setelah ibunya masuk ke dalam rumah, ia segera mengambil sapu dan mengusirku. Aku yakin dia membenciku setengah mati.
Namun kali ini, dia datang dengan membawa makanan, secuil daging ayam yang mungkin merupakan sebagian sarapannya pagi ini. “Puss… . Puss.. ,” ucapnya yang kuartikan dengan “Aku datang dengan damai! Terimalah salamku!”
Kudekatkan kepalaku pada tangannya dan sedikit menyundulnya manja. Lalu dengan perlahan aku mendekati tangan satunya dan memakan cuilan daging ayam itu. Rasanya hambar dan baunya juga tidak menggugah, tapi tetap kumakan sebagai bukti perdamaian kita. Sudah kubilang ‘kan? Manusia itu makhluk yang sangat mudah diperdaya. Hanya dengan gelayut manja, dia telah luluh padaku. Kini digendongnya aku dan dibawanya aku menuju motornya yang terparkir tak jauh. Dengan berpegang erat pada punggungnya, aku dibawanya mengendarai motor jauh dari rumahku yang nyaman. Aku tak tahu ke mana manusia ini membawaku. Namun manusiaku biasa menggendongku ke tempat mangkok makanku yang penuh dengan ikan kaleng yang sangat kunikmati. Aku yakin setelah makanan pembuka tadi, dia akan membawaku ke tempat di mana sajian utama berada.
Namun naas! Jalanan pagi itu begitu penuh sesak kendaraan. Ditambah panas menyengat punggungku membuatku bergerak tak nyaman. Namun tangan manusia itu menahanku. Dia pikir mungkin itu akan melindungiku tapi perasaan tidak nyaman menyergapku. Panas dan polusi membuatku berontak dan disitulah aku melompat dari rengkuhan manusia itu dan meluncur di aspal yang panas di bawah terik matahari. Jalan raya menjadi semacam rimba bagiku. Segalanya terlihat begitu besar dan seperti akan menginjak atau melindasku. Mobil besar menderu di depanku, dan entah karena kekuatan Ilahiah atau takdir atau naluri hewaniku atau ketiganya, kudapati diri tertarik menuju tepi jalan, menghindari ban yang menggelinding di bawah badan mobil besar itu. Entah bagaimana caraku mendarat ke tepi jalan, aku langsung bangkit dan berlari. Berlindung dari panas yang sepertinya tanpa akhir di jalan ini dengan pekikan manusia yang beradu dengan suara klakson serta decit ban yang direm mendadak di belakangku.
Aku berlari seperti tak pernah berlari sebelumnya. Suara klakson, deru mesin kendaraan, debu jalanan, trotoar berlubang, kaki-kaki manusia yang berjalan cepat, segalanya terasa menakutkan di sini. Jalanan aspal atau jalanan semen tidak ada bedanya, begitu panas membakar bantalan kakiku. Namun dengannya aku lebih cepat lagi berlari. Menyusuri jalan yang menurun, menerobos perempatan, melewati roda-roda motor-mobil yang mungkin dapat melindasku hingga rata dan orang yang memaki tanpa tahu untuk siapa. Lalu aku mulai berhenti di seberang perempatan itu
Melihat sekeliling, aku menyadari bahwa tempat ini adalah pasar seperti yang aku lihat pada televisi manusiaku. Ah, manusiaku… . Aku tidak tahu apakah aku akan kembali dan bertemu dengannya lagi. Namun kulihat lagi jalan yang telah kulewati dan jalan yang menurun itu kini terlihat begitu jauh. Aku begitu bodoh membiarkan anak manusia yang durjana itu membawaku pergi dengan ilusi surga penuh dengan ikan di pikiran. Namun apa hasilnya? Aku terduduk lesu di trotoar jalan yang menjadi tempat berjualan kembang.
Hari masih pagi, sedangkan jalanan semakin ramai dengan kendaraan dan manusia. Udara juga terlalu panas menyengat kulit di balik bulu-buluku. Namun kulangkahkan juga kaki-kaki gemukku, melanjutkan perjalananku entah ke mana.
Aku bukanlah kucing kurang pergaulan yang takut pada dunia luar seperti tetangga kucingku, Bleki. Sebaliknya, menjelajah komplek adalah kegiatan kesukaanku. Aku bisa mengganggu burung kenari, beradu kuat dengan Bombom dan Telon (teman kucingku yang lain), atau berkejaran dengan mereka. Namun segalanya yang begitu asing di sini membuatku ragu-ragu melangkah. Rumah-rumah di sini tidak berarsitektur seragam seperti di komplek manusiaku tinggal. Baru kusadar setelah jauh melangkah, rumah-rumah ini bukanlah rumah tempat tinggal biasa. Bangunan di sepanjang jalan ini adalah separuh toko.
Di salah satu toko yang sepi aku berhenti. Kulihat ikan yang menggiurkan di gambar yang tergantung di depan toko itu, lalu memutuskan untuk mampir menghiba sepotong ikan. Biskuit ikan yang diberikan oleh manusiaku dan cuilan ayam dari anak tetangga manusiaku yang durjana itu tadi pagi menguap dari perutku. Setelah maraton yang kulakukan pagi ini, aku lapar lagi. Begitulah, aku melompat menuju etalase yang menjadi sekat antara jalanan dan bagian dalam toko, mengeong pada entah siapa di toko tanpa penjaga ini.
“Tidak ada ikan di tempat ini,” meong seekor kucing dari balik kelambu mengejutkanku.
“Di gambar yang tergantung ada ikan. Terbujur, terjepit bambu, dan matang, tapi tetap ikan,” aku mengeong dengan lemah, memelas. Kemarin di waktu-waktu seperti ini biasanya aku menikmati sarapan jilid II yang disponsori tempat makan otomatis yang disediakan oleh manusiaku.
Kucing itu, yang ternyata seekor kucing kampung manis berwarna hitam dan putih, naik ke atas etalase agar sejajar denganku lalu mengeong menjawab, “Ikan itu hanya ada jika seseorang memesannya dan kita tak bisa memakannya walau ikan itu ada.” Aku tertunduk lesu mendengar jawabannya sampai akhirnya kucing itu melompat turun dan mengeong, “Tapi aku bisa membawamu ke Waruna, tempat kucing-kucing tak punya pemilik mencari makan.”
Secercah harapan datang. Aku mengikutinya dengan senang, “Terima kasih,” meongku.
“Tidak masalah,” balasnya. “Siapa namamu?”
“Teman-temanku mengikuti cara manusiaku memanggilku, ‘Ndut’. Siapa namamu?,” meongku senang membayangkan ikan.
“Namaku Kliwon, manusiaku memberiku nama itu karena aku dilahirkan di Hari Kliwon,” meongnya menjawabku, lalu langkahnya tiba-tiba menjadi lebih pelan dan menatapku curiga, “Kau memiliki manusia? Kenapa bisa kelaparan di jalan?” tanyanya.
“Seorang anak manusia tetangga membawaku terlalu jauh untuk pulang,” tundukku lesu.
Sepersekian menit Kliwon sempat terdiam kemudian melanjutkan berjalan. “Tidak masalah. Kucing-kucing di Waruna terbuka kepada pendatang baru. Meskipun di sana juga ada Bagong yang berkelahi dengan hampir semua kucing di Waruna,” meongnya semakin lirih di kalimat terakhir.
Kliwon menemaniku menyusuri jalan ramai ini. Melewati banyak rumah, toko, kantor desa, dan sekolah. Sesekali berhenti saat manusia-manusia itu mendekati kami untuk mengelus kepala dan menggaruk dagu kami. Walaupun pada akhirnya mereka pergi lagi tanpa membayar kita dengan biskuit ikan atau segalanya-ikan sebagai upah untuk kami yang telah menghibur mereka dengan bertingkah manis. Aku semakin lapar dan Kliwon tak segera memberitahuku berapa lama lagi aku harus menahan rasa laparku untuk santapan enak di Waruna, surga yang diceritakannya.
Aku tidak lagi merengek ketika jalan yang tadinya besar menyempit, Kliwon tersenyum, dan bau amis dan segar ikan tercium dari balik Balai Besar yang ada di depanku. Aku mempercepat jalanku menuju Waruna dan mendapati tempat terbuka dengan tiang dan atap tinggi yang di bawahnya masih ramai orang menjual dan membeli ikan, serta kucing yang dengan belas kasih manusia memakan ikan hasil sortir karena terlalu kecil atau terlalu lama di simpan. Kliwon mengajakku menuju sudut di mana manusia itu “membuang” ikan-ikan itu lalu memakannya.
Ikan-ikan yang ditunjuk Kliwon berbau busuk. Matanya yang merah seperti mengisyaratkan kata-kata penuh kutukan, “Berani-beraninya kau berpikir untuk mengirimku ke mulutmu yang bau lalu dicerna di perut neraka tanpa dasar milikmu itu!”. Aku melengos, menuju bak ikan yang lebih beraroma amis dan segar. Ada manusia di dekat bak ikan itu – namun seperti yang kuyakini – manusia adalah makhluk yang paling gampang untuk diperdaya, dia akan memberikan ikan yang besar dan indah itu padaku seraya memberikan belaian sayang pada kepalaku. Setidaknya itulah yang tergambar di kepala mungilku, sampai usiran dan bentakan lah yang kudapat. Aku menghindar menjauh dari sabetan kaos manusia itu yang tadinya dipakai di kepalanya.
Kucing-kucing di sana menertawakanku. Beberapa mengeong mengejek, “Dia terlalu naif untuk berpikir bahwa manusia lah sang maha pengasih.”
“Padahal manusia lah makhluk terkejam di muka bumi,” kucing lain mengeong menanggapi.
Kliwon mengeong memanggilku kembali. “Tahu tempatmu! Tidak akan ada yang memberimu ikan-ikan segar itu, apalagi ikan beraroma laut itu di sini. Ikan itu sangat berharga. Makanlah ikan-ikan ini,” omelnya setelah aku kembali.
Aku menunduk mengeluh, “Ikan ini begitu menyedihkan. Matanya menyala merah.”
“Dengan sikapmu kau tidak akan mendapatkan apapun. Makanlah dengan menutup matamu,” meongnya.
Aku mencoba memakan ikan itu dengan mata tertutup. Kudapati diriku mulai terbiasa dengan baunya dan rasa ikan itu bahkan lebih baik dari ikan kaleng yang diberikan manusiaku dulu. Aku mungkin akan bertahan di sini, pikirku penuh harapan sedetik sebelum cakaran mengenai pelipis dekat mataku yang tertutup. Ketika kubuka kedua mataku, kulihat seekor kucing dengan warna bulu yang sama denganku meskipun lebih besar dan berotot, menatapku marah.
“Beraninya kau datang ke sini dan menginginkan ikan yang bahkan tidak pernah kudapatkan,” geramnya. Ia melirik sekilas ke arah Kliwon yang menatapku khawatir lalu mengeong “Ditambah kau datang dengan selirku, Kliwon?” Setelah itu, baru kutahu bahwa dialah Bagong, si kucing yang diperingatkan Kliwon tadi dengan setengah berbisik.
Aku balas menggeram, tidak terima telah ditampar saat makan dan dituduh tidak-tidak oleh kucing menyeramkan itu. Aku sudah berancang-ancang untuk menyerangnya balik, namun tangan Bagong lebih cepat menerjangku. Giginya yang kuat entah bagaimana telah menancap di bahuku, membuatku menjerit karena sakit. Cakarnya juga tak ketinggalan berkali-kali hadir saat dia memukuliku. Dalam keadaan terdesak karena pertarungan yang tidak seimbang serta pergerakanku yang tidak luwes karena berat badanku yang berlebihan, aku bukannya kabur saat Bagong melepaskanku malah mengejar untuk membalas. Tanganku akhirnya mengenainya, namun sayangnya kuku yang absen karena manusiaku selalu memotongnya ketika panjang tak memberikan dampak apapun di badan Bagong yang kekar. Sebagai balasan, dibantingnyalah aku seperti seorang pegulat di televisi.
Sudah jelas aku akan babak belur sendiri di sini dengan Bagong menyerangku membabi buta. Tak kuasa membalas, pikiran untuk kabur terlintas di kepala. Namun sebelum aku kabur, Bagong telah mengambil ancang-ancang untuk menyerangku lebih brutal lagi. Tibalah di udara, saat Bagong tepat berada di atasku, kurasakan air dingin dan amis mengguyurku. Mengguyur kita berdua! Manusia-manusia itu tidak tahan dengan geraman dan meongan kita yang bersahut-sahutan, lalu memutuskan untuk menyiramkan air dingin bekas es pengawet ikan yang mencair kepada kita berdua. Aku memanfaatkan momen itu untuk kabur entah ke arah mana. Melewati rumah penduduk dan menerjang jalan raya. Salah satu kendaraan yang lewat membunyikan klaksonnya karena kaget melihatku lewat. Badanku terpeleset mencoba menghindari roda kendaraan, namun aku terus berlari jauh dari Bagong. Ketika sudah cukup jauh, baru aku berhenti.
Bahuku mengucurkan darah di tempat Bagong menancapkan giginya. Sakit sekali hingga membuatku menjilat lukanya. Badan gemukku begitu payah dan aku merasa sangat letih. Aku merebahkan diriku pada lantai kayu. Dengan terus menjilat lukaku, aku meringis sakit. Setidaknya aku telah jauh dari Bagong, meskipun itu berarti aku juga jauh dari Kliwon dan ikan-ikan itu.
Lantai tempatku merebahkan diri berdecit. Gerombolan manusia melewatiku dengan membawa gulungan tali tampar. Baru kusadari bahwa tempat ini adalah dermaga, seperti yang kutonton dari gambar bergerak pada layar gawai lebar manusiaku dulu saat dia ingin menunjukkan di mana ikan-ikan itu berada. Lalu nun jauh di ujung dermaga ini, akan kudapati laut membentang luas – meski yang terlihat dari sini hanyalah tiang-tiang kapal yang tinggi. Bicara soal kapal, mungkin kapal itu lah yang mengangkut ikan-ikan dari laut lepas untuk diolah di Pabrik dan menjadi makananku.
Aku tertegun menyadari betapa dekatnya aku dengan laut. Mungkin anak laki-laki manusia tetangganya yang durjana itu tidak membawanya ke tempat di mana makanan berada, tapi kaki gemukku sendiri lah yang membawaku ke sana. Dengan penuh harapan dan bayangan tentang ikan di kapal-kapal besar itu, aku mencoba bangkit dan melangkah dengan tertatih ke ujung dermaga.
Namun belum sampai setengah jalan menuju ujung dermaga, kudengar meongan dari kucing yang duduk santai di pinggir jalan dermaga, “Tidak ada ikan di tempat ini. Kau mungkin akan mendapatkannya sekali dua kali saat nelayan itu pulang melaut yang kita semua tahu betapa jarang peristiwa itu terjadi. Kau harus kembali ke Waruna jika ingin mendapatkan makanan dan menghadapi Bagong,” meongnya bijak. Pada kalimat terakhir dia melirik lukaku yang masih basah.
“Siapa kau? Bagaimana kau tahu tidak ada ikan di sini, di laut tempat ikan-ikan berasal?” meongku tak percaya.
“Aku Mugi, kebetulan tinggal di sini begitu lama sehingga mengetahui betapa lamanya menunggu ikan di sini daripada di Waruna,” jelasnya.
“Bagaimana bisa? Bukankah banyak kapal di sini?” cecarku tak terima.
Mugi bangkit dari tempatnya merebahkan diri lalu berjalan pelan ke ujung dermaga. Perjalanan begitu panjang dengan kaki mungilnya dan kaki gemukku yang terluka menapak lirih. Pada langkah kakinya yang lirih kudengar dia mengeongkan sebuah kisah untuk menjawab pertanyaanku, “Kapal-kapal besar di belakangku? Kapal-kapal itu tidak mengangkut ikan. Nitrogen, amonia, urea. Itulah yang mereka angkut kata orang-orang di sini. Lalu kapal kecil yang bersandar di dermaga ini lebih banyak mengangkut orang, kau tahu, sebagai angkutan penyeberangan. Itulah mengapa lebih banyak ikan di Waruna daripada di sini. Sebagian besar ikan di Waruna berasal dari tambak dan pada waktu-waktu tertentu tidak ada ikan dari laut, meskipun laut hanya berada di ujung sana. Nelayan di sini jarang melaut, terlalu jauh jarak yang ditempuh untuk bisa mendapatkan ikan dan dengan jarak yang terlalu jauh itu bahan bakar yang dibutuhkan semakin banyak. Selama kapal-kapal industri itu wira-wiri di perairan ini, tidak ada ikan di tempat ini.”
Di ujung dermaga dengan laut yang ternyata tidak bisa kulihat luas lapangnya karena terhalang kapal-kapal raksasa yang tidak mengangkut ikan itu, ada patah hati yang tidak bisa disembuhkan dari kebohongan yang disampaikan dongeng-dongeng gambar bergerak pada layar gawai lebar manusiaku tentang ikan, laut, dan katastrofi. Aku salah mengira bisa memperdaya manusia. Manusia itu yang telah memperdayai aku.
Miftahul Wulandari. Mengenyam pendidikan tinggi di jurusan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Penyuka kucing. Saat ini sedang berkegiatan di bidang kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
Residensi Literatutur mengundang 18 Penulis di Indonesia untuk diundang ke Gresik dalam upaya melakukan pembacaan, penggalian ide, dan menemukan gagasan atau kemungkinan lain yang kemudian dituangkan dalam cerita pendek. Residensi ini diadakan oleh Yayasan Gang Sebelah yang didukung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Gang Sebelah
Yayasan Gang Sebelah didirikan pada Tahun 2017, sebagai bentuk upaya dalam melakukan penelitian, pengarsipan dan pengembangan Kebudayaan.