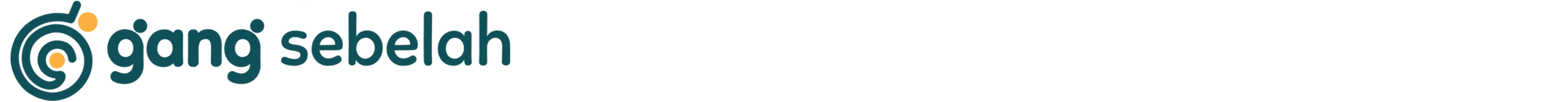Aku datang ke pesisir pantai saat gerimis turun. Malam itu, tiga orang keluar dari angkutan, menggedor-gedor rumah reyot yang dindingnya didominasi seng. Seorang perempuan tua keluar, lekas ditarik paksa. Perempuan tua itu meronta, setua itu tubuhnya masih terlihat perkasa. Di utara, air laut sudah tinggi. Bulan-bulan ini, warga pesisir sudah akrab dengan banjir rob. Tetapi, ini bukanlah ajakan untuk mengungsi, lantaran perempuan tua itu menyebut satu nama dengan berteriak penuh amarah. Tiga orang berwajah dingin itu, seperti tak peduli, dan mendorong tubuh rentanya masuk ke dalam angkutan berwarna kuning. Aku tertegun menyaksikannya dari jarak yang tidak bisa dikatakan jauh, tetapi tidak sedekat pandang mata mereka bisa menangkap. Tubuhku bergeming, tak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah ada perasaan ganjil yang menyuruhku diam dan bersembunyi.
Laki-laki lain bertubuh kekar, menendang dan memukul tiang penopang rumah reyot itu hingga ambruk. Terdengar teriakan melengking dari angkutan yang melesat ke arah selatan. Laki-laki itu menyusul mengendarai honda CG merah setelah diungkal hingga tiga kali.
Biadab, gumamku. Aku mengutuki diriku sendiri lantaran ketidakmampuanku berbuat apa-apa. Apalagi, ini adalah satu-satunya cara menyambung sesuatu yang putus lima belas tahun silam. Aku pun gegas berlari, sebelum sisa bangunan rumah itu tergenang rob. Dan aku benar-benar kehilangan. Deras hujan dan suara petir, mengaburkan kewaspadaanku. Aku mengais, memindah segala hal yang saling tindih menimpa. Hingga pada waktu yang tidak aku sadari, sebuah benda keras menimpa leherku. Mataku berkunang-kunang, lalu memendar. Semua jadi gelap.
Jika bukan karena Mardja, aku tidak akan bersusah payah pergi ke kota ini. Memenuhi firasat yang berulang kali hinggap.
Baiklah, kita mundur dua belas jam sebelumnya. Saat aku baru sampai ke kota G. Aku menyusur jalan Raden Santri menuju ke satu tempat yang menyimpan cerita lama. Satu tempat yang selalu ia datangi, bioskop Wisma Hartatik. Gambar hiu putih dari dalam laut hendak mencengkram seseorang yang sedang berenang terpampang dalam poster di atas pintu masuk. Di bawahnya tercetak tulisan “INI HARI”. Film Jaws garapan Steven Spielberg sedang populer di berbagai tempat. Meski begitu, aku ingat temanku ini begitu membenci penayangan film barat. Herannya ia malah gemar datang ke bioskop ini ketimbang ke bioskop Kencana yang dikenal kerap menayangkan film-film Indonesia.
Rupanya, aku tahu alasannya, ketika ia tiba-tiba pamit di suatu malam. Aku duduk di tempat yang sama, lima belas tahun lalu, memegang majalah Liberty dengan sampul Chitra Dewi yang memegang payung dan tersenyum manis. Belakangan, ketika dalam perjalanan ke kota G, beberapa kali aku melihat baliho bergambar Chitra Dewi yang sedang mempromosikan Jamu Jago. Film Tiga Dara meledak saat itu, Mardja beberapa kali menceritakan alur film garapan Usmar Ismail itu dengan antusias. Belum saatnya masuk jadwal penayangan film, ia menghampiriku sambil mengulurkan sebatang rokok Grendel Utama, gegas aku menggamit dan menyulutnya.
“Aku akan ikut Hamid ke Tirana,” ucapnya. Mardja menatapku lekat, mengharap persetujuan. Mulutku benar-benar terasa hambar saat itu, antara haus atau kerongkonganku mendadak kering diserap kebodohan kawanku ini.
“Hamid siap bantu urus semuanya, dari pada jaga bioskop, dan berharap orang jerman itu menyetop film mereka, aku bisa mati bodoh di sini.”
Benar kata Mardja, mengharap Wisma Hartatik berhenti menayangkan film barat, sama halnya menunggu gajah bertelur. Hartman, si pemilik bioskop rutin membayar pajak dan mau rutin mengirim santunan ke pondok Kiai Zuber. Apalagi, di depan pintu masuk bioskop mereka menyewa preman penjaga pasar ikan, Kang Komar CS. Kalau mau mengusik, sama halnya ngajak bentrok. Untung benar, simpatisan partai yang Mardja ikuti dapat izin menyewa gedung lama bekas peninggalan kantor pelelangan ikan milik belanda di pesisir utara. Itu pun mesti bayar pajak dobel, ke pemerintah dan ke…. ah, sebenarnya tidak perlu kuceritakan ini lebih detail padamu. Karena aku tak ingin membuatmu—sebagai pembaca yang santun—menuduh golongan hijau dengan hal yang bukan-bukan.
Marah karena obrolannya tidak kutanggapi, ia merebut majalah Liberty dari pangkuanku. Lalu, membuka dengan kasar halaman demi halaman. “Lihat! Cerita ini tidak bermoral!” ia menunjuk sebuah cerita bergambar dengan judul “Gadis Jelita dalam Operasi C.I.A (7)” nampaknya sebuah cerita bersambung,
“Apalagi itu!” ia menunjuk poster film di atas pintu masuk bioskop. Seorang perempuan mengenakan rok putih dengan badan bagian atas hanya tertutup beha berwarna putih. Aku kenal perempuan itu. Janet Leigh, artis perempuan pemeran film horor psikopat yang sedang naik daun. Ia amat membenci film barat yang lebih mengajarkan liberalisme. Satu dari dua ideologi yang ingin ia berangus, lainnya kapitalisme. Ia menilai pembangunan pabrik-pabrik di pesisir pantai kota G, dikhawatirkan melanggengkan sistem kapitalisme yang sudah kentara ia rasakan.
Aku tidak melarangnya pergi bersama Hamid, pun tidak mengiyakan. Pertanyaanku padanya hanya dua, kau ini anak tunggal, bagaimana dengan ibumu? Ia menjawab, ada bapak. Bagaimana kalau tiba-tiba bapakmu mati? Ia diam sebentar. Sebagai keluarga pendatang, yang selalu berpindah-pindah mengikuti dinas bapaknya di tentara angkatan darat, Mardja memang tidak sepenuhnya percaya bahwa menjadi anak tentara menjamin keamanan keluarganya. Terlebih, beberapa kali ia bercerita padaku, banyak terjadi bentrok simpatisan partai kiri dengan masyarakat santri di daerah barat. “Hanya tinggal menunggu waktu saja,” bisiknya kemudian.
Belakangan, bapaknya dibayar secara diam-diam menjadi bekingan pembangunan pabrik industri di daerah pesisir. Pembangunan yang sebenarnya tidak ia setujui lantaran menyalahi prinsip sosialis dalam dirinya. Aku pernah menasihatinya, cepat atau lambat bapaknya akan mengetahui aktivitasnya di partai. Tetapi ia memilih abai dan meyakinkanku semua akan baik-baik saja. Suatu pagi, ia bertengkar hebat dengan bapaknya. Dan satu giginya tanggal akibat pukulan yang juga membuat matanya biru waktu menceritakan padaku.
“Laki-laki brengsek itu tidak ingin anaknya terlibat dengan urusan politik, apalagi membawa-bawa urusan kesetaraan. Sesuatu yang tidak akan bisa dimakan.” ucapnya geram.
Betapapun besar keinginan Mardja untuk pergi, aku tahu ia amat mencintai ibunya. Ibu Mardja adalah satu dari sekian banyak perempuan di dunia yang kawin dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Meski begitu, tak terhitung bagaimana ibu Mardja sangat mencintai anaknya. Maka, ketika seminggu kemudian Mardja menelponku, darahku naik hingga ke ubun-ubun kepala.
“Aku nitip ibu,” ucapnya lirih penuh keraguan. Aku mengumpat, mengatai dirinya anjing egois! Mardja memilih pergi bersama Hamid dan rombongan mahasiswa lain ke Albania. Mengikuti program pemerintah yang mengirimkan mahasiswa secara besar-besaran ke berbagai negara. Pilihan bodoh yang menyelamatkan sekaligus menyengsarakan hidup ibunya.
Berbulan-bulan setelah ia pamit, aku diterima kerja di Jakarta menjadi salah satu wartawan majalah Intirasa. Mardja tidak pernah berkabar. Aku malah beberapa kali berkirim pesan dengan Hamid, sahabatnya. Aku mengabarkan keadaan tanah air sedang genting. Beberapa kabar kudengar dari timur, bentrokan santri dengan simpatisan partai kiri semakin menggila. Apalagi di daerah pesisir, tempat tinggal orang tua Mardja, pembangunan pabrik mulai dikecam ratusan warga yang tergabung dalam berbagai aliansi. Kudengar, terjadi PHK massal pada keluarga buruh yang ikut berdemo. Melalui Hamid, aku diminta Mardja untuk datang ke sana, paling tidak memastikan kabar keluarganya. Tetapi, ajuan liputanku di daerah pesisir ditolak, terlalu berbahaya kata redakturku. Aku tidak benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa teman wartawan justru sibuk mencari informasi ke istana. Sedangkan dari berbagai daerah mulai kudengar isu-isu yang tidak mengenakkan.
Segalanya begitu cepat berlalu. Petaka di akhir September enam lima membuat keadaan semakin runyam. Alih-alih datang ke kota G, aku justru kehilangan kontak dengan Hamid. Kudengar, Hamid, Mardja, dan semua mahasiswa yang dikirim ke berbagai negara tertahan. Kedutaan besar Indonesia di negara-negara itu melakukan skrining. Dan mereka yang enggan tunduk pada pemerintah yang baru akan dituduh berafiliasi dengan partai kiri. Tak terkecuali Mardja, ia pasti menolak tunduk. Apalagi, telah ia himpun beragam data dan argumen bahwa pemerintah yang sekarang berkuasa kelak akan membawa bencana. Suatu hal yang awalnya tak kumengerti, lantas aku menerima akibatnya.
Aku pun kaget, ketika mendengar beberapa tentara kedapatan berafiliasi dengan partai kiri. Termasuk bapak Mardja. Kabar ini kudapat dari seorang nelayan yang menceritakan kisah seorang janda tua yang tinggal di pesisir. Konon, suaminya mantan tentara yang ikut dieksekusi di pesisir. Ia kedapatan menjadi mata-mata partai kiri, suatu hal diluar nalarku selama ini. Janda tua itu, katanya masih bersetia menunggu anak semata wayangnya pulang. Berharap bisa menjemputnya di dermaga dan menceritakan betapa tanah air yang mereka cintai justru merenggut satu per satu orang yang dicintainya.
Seperti yang terjadi padaku saat ini. Dengan tangan terikat, aku didorong dengan kasar menyusur jalanan dermaga yang tergenang air. Nampaknya rob semakin tinggi. Kulihat ke arah jauh, terlihat kerlap-kerlip tiang penopang besi yang tinggi. Pembangunan terus berlanjut meski darah mengucur membasahi laut. Wajahku perih ditimpa gerimis. Seseorang menyuruhku berbaris sejajar menghadap laut. Satu per satu nama dipanggil, ditanyai, disumpah atas nama Tuhan, kemudian terdengar suara golok mengiris diiringi serak tenggorokan yang begitu mengerikan. Tubuh-tubuh jatuh ke laut, menggenang merah.
Pada selang waktu yang tak bisa kuterka berapa lamanya, aku tak bisa menyalahkan siapapun selain kebodohanku sendiri nekat datang ke kotamu, Mardja. Kemudian, terdengar suara memanggil. “Sumardja! Kau kah Sumardja!”
Tiba-tiba punggungku ditendang, hingga tubuhku jatuh ke depan. “Jawab, cuk!”
“Sssst, sabar Kang, seperti pesan mbah,” terdengar suara halus menenangkan.
Aku mencoba menoleh ke belakang, tetapi kaki sialan itu kembali menendangku.
“Saudara Sumardja, anda akan saya bunuh, tetapi sebelum saya bunuh apa anda ada pesan? Kalau anda orang Islam, seharusnya membaca kalimat syahadat dulu!”
Aku menatap kerlap-kerlip cahaya lampu, kupikir inilah saat yang tepat menyelamatkan ibumu, Mardja. Tenggorokanku yang kering tak kuasa berucap apapun, hanya anggukan. Aku tak akan mengelak mengakui namamu dan mengharap keselamatan ibumu.
Kupasrahkan pada nasib dan kebodohanmu, Mardja. Ah tidak, kebodohanku yang nekat datang, meski aku tahu kau takkan tega memintanya. (*)
Ponorogo, November 2023
Untuk yang berjuang, di tengah kehilangan
lahir di Banyumas, kini tinggal di Ponorogo. Berkarya sebagai Kepala Humas Kampus Literasi STKIP PGRI Ponorogo. Ketika menjadi Ketua Program GMB-Indonesia, pernah memecahkan dua rekor Muri di bidang literasi. Karya-karyanya telah tersebar di pelbagai media lokal dan nasional baik cetak maupun daring. Buku kumpulan cerpennya berjudul, “Di Hari Kelahiran Puisi” dan “Bulan Ziarah Kenangan”. Kini menyibukkan diri sebagai pendaras media lensasastra.id, berkomunitas di Sutejo Spektrum Center (SSC), menjadi bagian dari Booktube Indonesia, dan sebagai penjaga toko buku @jbb_bookstore. Bisa dihubungi melalui IG: @saptaarif atau surel saptawnd@gmail.com. WA: 085716286686.
Residensi Literatutur mengundang 18 Penulis di Indonesia untuk diundang ke Gresik dalam upaya melakukan pembacaan, penggalian ide, dan menemukan gagasan atau kemungkinan lain yang kemudian dituangkan dalam cerita pendek. Residensi ini diadakan oleh Yayasan Gang Sebelah yang didukung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Gang Sebelah
Yayasan Gang Sebelah didirikan pada Tahun 2017, sebagai bentuk upaya dalam melakukan penelitian, pengarsipan dan pengembangan Kebudayaan.